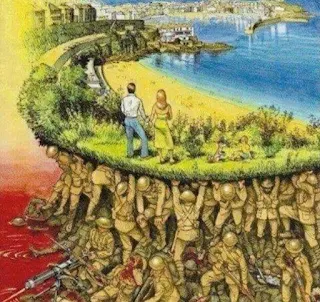|
| source photo: sinarharapan.co |
Tiga hari berpeluh kesah di jalan,
tepat di depan istana kekuasaan. Tangis dan "histeris" sekitar 442
ribu guru honorer K2, tak kunjung mampu mengetuk nurani kuasa. Apa boleh buat,
pulang tanpa kejelasan, justru dibuai dengan cibiran sinis, sebuah cibiran
seolah ingin memaksakan kredo bahwa guru sudah seharusnya miskin. Dan demo
dianggap sebagai perilaku tidak terpuji.
Nasib yang didaku “pahlawan”,
dipaksa menerima imajinasi tentang kemuliaan status, di saat yang sama juga
harus menerima kesialan dalam nasib. Tak hanya berusaha melawan kekuasaan yang
ingkar, tapi juga harus menepis tudingan cibiran dari sebangsanya yang terjebak
dalam kesalahan berpikir. Salah satunya, tulisan yang katanya dari mantan guru
honorer, menganggap demo guru sebagai tindakan memalukan! (baca: http://jetjetsemut.blogspot.co.id/2016/02/guru-demo-memalukan-surat-terbuka.html). Cukup naïf bukan?
Cibiran dan sinisme terhadap demo
guru, mulai yang menganggap demo guru sebagai perilaku tidak terpuji hingga
yang menganggapnya sebagai "memalukan", tak lain merupakan
tuduhan-tuduhan yang sebenarnya lahir dari cara berpikir yang keliru (fallacy).
Di antaranya: Kesalahan berpikir
pertama, adalah mengaggap demo guru sebagai bentuk pengemisan kepada negara.
Jelas, cara berpikir ini keliru secara fatal. Kenapa?. Karena guru datang untuk
menuntut hak, bukan meminta welas asih. Itu karena, relasi guru dan negara,
seperti dengan relasi sipil dan kekuasaan, yakni ada hak dan kewajiban yang
harus saling memenuhi. Hidup layak adalah hak semua warga negara tanpa
terkecuali, tentu itu amanah bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang 1945
Pasal 27 ayat 2.
Guru dan buruh tentunya sama dalam
konteks ini, demonstrasi buruh adalah bentuk tuntutan akan hak, bukan welas
asih. Ada hak yang tidak terdistribusikan dengan adil oleh pengusaha dan
negara. Mengingkari pemenuhan penghidupan layak bagi warganya, sama halnya
dengan mengingkari konstitusi. Apalagi konkret, kehadiran guru untuk berdemo,
juga dipicu oleh janji politik yang bertebaran saat pencapresan sebelumnya. So,
apa yang salah?
Kesalahan berpikir kedua, adalah
memaksakan cara berpikir asketis yang berkarater penghisapan (bukan asketis
yang berkarakter revolusioner). Seolah tugas yang dianggap “mulia” itu, harus
miskin dan penuh penderitaan. Penderitaan-penderitaan harus diterima dengan
lapang dada. Ironisnya, penderitaan-penderitaan itu diharuskan diterima bukan
karena pilihan, tapi lebih ke paksaan.
Kesalahan berpikir ini sama kalau
ada orang datang dan berkata, “Saya miskin”, “Itu karena kamu malas”, “Lho,
gimana malas, tiap hari saya bekerja dari pagi sampai malam?”, “Berarti itu
karena kamu hidup, coba tidak hidup, kemiskinan kamu hilangkan?”. Sama dengan
cibiran yang menganggap, “Kalau kamu mau hidup berkecukupan, ya jangan jadi
guru!”. Seolah-olah guru harus ditakdirkan miskin. Padahal persoalan miskin,
tidak miskinnya guru, bukan terletak pada profesi guru itu sendiri, tapi lebih
ke sistem yang memiskinkan profesi itu. Sistem inilah yang dilawan para guru.
Tentu guru juga bukan menuntut untuk kaya, tapi setidaknya hak untuk membeli
buku, itu penting!
Logika tersebut sama halnya kalau
ada yang orang yang datang dalam keadaan lapar, lalu dijawab dengan menyuruh
mereka ibadah. Lapar dihakimi sebagai nafsu, padahal ia realitas alami. Lalu
diambillah kesimpulan, “Cepat lapar, karena kurang berdzikir!, makanya
perbanyak dzikir!”. Cara berpikir asketis berkarater penghisapan inilah, yang
melanda dan merundung bangsa kita hari ini, yang membuat kita terus berada di
garis terbelakang (kondisi-kondisi ini pula yang mendorong Tan Malaka menulis
Madilog, untuk meluruskan cara berpikir bangsa ini!).
Ada kecenderungan menerima suatu
kenyataan, tapi tidak mampu menemukan sebab konkrit antara kenyataan yang
dialami dengan realitas sosial yang terjadi. Contoh lainnya, sama halnya kalau
ada yang berkata, “Biarkanlah pejabat korupsi, peduli amat!, toh nantinya juga
dia masuk neraka”. Meminjam istilah Cak Nur, kesalahan berpikir ini, karena
meng-ukhrawikan dunia, tidak bisa membedakan dunia dan akhirat. Korupsi
persoalan dunia, dan neraka persoalan akhirat, lalu persoalan dunia ingin
diseleseikan dengan jawaban akhirat.
Alasan untuk terlepas dari persoalan
sosial dianggap sebagai kebaikan, tercandukan dengan hipokrisi imajinasi
tentang yang abstrak, sebagai alasan untuk berpaling menolak yang rill.
Ibaratkan kakinya di bumi, tapi tangannya dilangit. Menggelantung!
Hal itu sama kalau ada orang
berkata, “Biarkanlah kita jadi guru dengan upah yang tidak memanusiakan (atau
ditindas), nanti di surga kita rasakan manfaatnya!”. “Semakin ditindas, semakin
membuat kita mulia, kita mulia karena ditindas”. Logika seperti ini, saya bisa
bilang, adalah bentuk nyata bahwa pembodohan ala kolonial masih bercokol di
pikiran masyarakat sampai saat ini.
Ini mirip dengan perkataan yang
menganggap penderitaan (meskipun bukan karena pilihan, melainkan paksaan),
penderitaan adalah bentuk kedekatan dengan Tuhan, semakin menderita semakin
dekat dengan Tuhan. “Toh, semuanya juga karena Tuhan, kita miskin karena dicoba
Tuhan, kita kaya juga karena dicoba Tuhan”. Menurut saya kesalahan berpikir
tersebut, alih-alih mentauhidkan diri, justru sebaliknya, mensyirikkan diri.
Kenapa?. Karena menganggap derita (karena ditindas) pun dari Tuhan! (maha suci
Tuhan dari segala tudingan miring seperti itu!).
Yang saya ingin katakan, bukankah
agama justru diutus untuk mengajak manusia berpikir, dan menemukan akar
persoalan kemanusiaan yang terjadi, lalu diwajibkan manusia untuk menyeleseikan
persoalannya sendiri, itulah agama yang saya pahami. Apa artinya?, kalau
persoalan sosial terjadi, itu berarti itu juga harus ditemukan sebabnya di
kehidupan itu sendiri. Guru tidak diupah dengan layak, itu bukan takdir yang
harus diratapi dengan kegembiraan, tapi itu penindasan yang harus dilawan.
Penindasan itu persoalan kemanusiaan. Itu berarti, persoalan guru adalah persoalan
kemanusiaan.
Jadi, apakah tindakan guru berdemo
adalah perilaku tidak terpuji?. Menurut saya, itu langkah konkrit untuk
menjalankan perintah agama, mencari jalan atas persoalan sosial, dan bergerak
untuk menuntut karena hak. Justru ketika tidak ada riak untuk mempersoalkan
ketidakadilan yang terjadi, disitulah pertanda bahwa agama telah membeku dalam
pikiran, yang tertinggal hanya hafalan. Kenapa?. Karena membiarkan
ketidakadilan dan perampasan adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap agama!
Meski terlalu jauh berbicara agama.
Tanpa membincangkan agama pun, kita bisa menerima pengwajaran atas demo guru.
Ini saya singgung, karena banyak yang sinis, justru menggunakan argumen-argumen
keagamaan, yang menurut saya cukup dangkal. Cukuplah sejarah masa lalu yang
menjadikan agama sebagai alat untuk menindas, menindas sejak dalam pikiran!
Saatnya harus menjadi kekuatan pembebas, membebaskan sejak dalam pikiran!
Kesalahan berpikir ketiga,
menganggap demo adalah tindakan tidak terpuji dihadapan siswa?. Justru saya
ingin katakan, bukankah sebaliknya? Membiarkan ketidakadilan adalah justru
perilaku tidak terpuji di hadapan siswa. “Realitas demo dianggap tidak terpuji
dimata siswa”, sebenarnya adalah pemikiran yang lahir sebagai buah dari sistem
pendidikan yang nyata terlepas persoalan kehidupan saat ini. Moral yang disemai
di sekolah selama ini, memang bias dengan karakternya yang elit borjuis.
Moralitas pentaklikan terhadap otoritas, yang dianggap terpuji. Karkater yang
penuh kepatuhan (beda sedikit dengan kesialan) yang dianggap terpuji.
Ini sama dengan banyaknya orang yang
beranggapan bahwa, tipikal siswa yang dianggap terpuji di sekolah, adalah yang
bisa diam, tidak banyak protes, menerima segala sesuatunya dengan lapang dada,
meski itu adalah kesalahan. Guru adalah kebenaran, meskipun guru tidak benar,
ia harus diterima sebagai benar, menolaknya adalah perilaku tidak terpuji.
Buah dari kesalahan itulah yang
membuat kita memposisikan, bahwa demo guru tidak terpuji. Padahal sebaliknya,
ini adalah bentuk pembelajaran terbaik kepada siswa, akan bagaimana agar
pemahaman hak dan kewajiban yang dilafalkan tidak sekadar mengendap dan membeku
dalam kepala. Bahwa butir-butir pancasila, tentang keadilan dan kesejahteraan
bukan sesuatu yang terberi, melainkan realitas yang harus diperjuangkan terus
menerus.
Seperti halnya para pendiri bangsa
yang berjuang menegakkan pancasila, kita pun sama, hari ini berjuang agar
pancasila dijalankan, dari banyaknya orang yang ingin merongrong keberadaannya,
salah satunya lewat pengingkaran kekuasaan terhadapnya. Kesalahan berpikir
keempat, cibiran lahir, karena sang pencibir terlalu naïf, sulit membedakan
mana kebaikan dan mana keadilan. Kebaikan dan keadilan, dicampurbaurkan,
seperti tidak bisa menarik garis pembeda di antaranya. Contohnya: guru yang
menuntut keadilan, justru dihakimi secara moral, dengan mengaggap itu
memalukan, tidak terpuji dan sejenisnya. Mirip dengan kebiasaan sebagian
masyarakat, yang ketika ada perdebatan-perdebatan objektif, justru dihakimi
dengan penilaian-penilaian subjektif. Perbincangan persoalan sosial justru
dibalas dengan caci maki personal. Mirip kebiasaan sebagian politisi kita, saat
suasana debat gagasan, ketidakmampuan untuk memberikan respon logis, justru
akan berujung pada peghakiman personal.
Kita harus paham bahwa, kebaikan itu
pilihan, ia realitas subjektif yang melekat, dan dipilih secara sadar tanpa
paksaan. Kalau Anda, membantu orang lain, tapi karena dipaksa, maka apa yang
Anda lakukan belumlah bisa disebut wujud hakiki dari kebaikan. Atau yang kedua,
membantu karena motif yang terselubung, juga belum bisa disebut kebaikan.
Sedangkan keadilan dan ketidakadilan, ranah pembincangannya adalah hak.
Kalau Anda menyumbang, memberikan
hak Anda dengan ikhlas, itu kebaikan. Tapi kalau Anda bekerja selama 5 bulan
tapi tidak diupah, itulah ketidakadilan. Kenapa?. Karena ada hak yang tidak
didistribusikan. Ada keringat yang yang terhambat, sebab Anda bekerja untuk
bertahan hidup bukan? Kalau buruh bekerja berbulan-bulan tapi tidak diupah, dan
menerima itu dengan lapang dada, apakah karena ia baik? Tidak, itu kebodohan
namanya, ia harus disadarkan. Kenapa? Karena ia datang untuk bekerja, dan dari
bekerja untuk bertahan hidup dan menghidupkan!. Berarti membiarkan buruh dan
guru dengan upah yang tidak memanusiakan, sama halnya dengan membunuh mereka
secara perlahan-lahan, atau membunuh kemanusiaan itu sendiri. Bukankah hak
untuk hidup, adalah hak asasi?