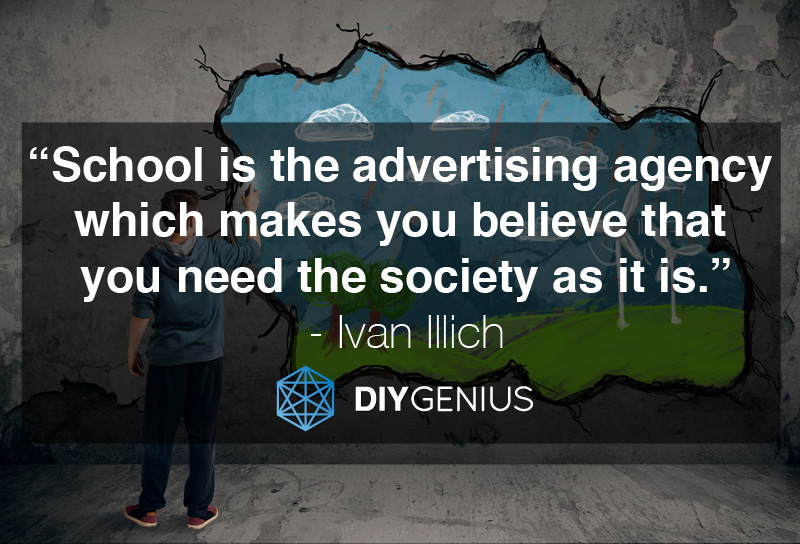|
| sumber gambar: https://bumirakyat.files.wordpress.com |
Terhitung sejak terpilih sebagai
presiden, Jokowi kini terbilang gencar mendorong penguatan sekolah
kejuruan. Bukan hanya dari target penambahan sekolah kejuruan hingga 300-an
lebih, juga September yang lalu, Presiden menandatangani Inpres bernomor 9
tahun 2016, yang isinya mendorong dan mendukung percepatan revitalisasi sekolah
kejuruan yang berorientasi kebutuhan pasar.
Persoalan ketenagakerjaan yang
menjadi persoalan bangsa menurutnya harus diseleseikan dengan penguatan
revitalisasi sekolah menengah kejuruan yang ada. Tentu saja asumsi yang
mendasarinya adalah, karena kapasitas sumber daya manusia kita yang masih
rendah, sehingga sulit diserap dalam dunia industri. Bahkan dalam Inpres tersebut,
Presiden juga menginstruksikan kepada Kemenristek agar memprioritaskan (pembukaan)
program-program kejuruan terapan di perguruan tinggi.
Alasan untuk itu semua adalah,
bahwa pendidikan yang ada sekarang ini dianggap kurang tanggap terhadap
perkembangan kebutuhan-kebutuhan pasar akan tenaga kerja. Semangat yang
mendasari prospek kebijakan ini adalah, pendidikan harus mampu menjadi penyalur
tenaga kerja mumpuni ke depan. Sekolah maupun perguruan tinggi harus lebih
mampu bersinergi dengan dunia usaha, agar bisa melahirkan generasi dengan ilmu
terapan dan keterampilan yang memadai.
Perspektif kebiajakan pendidikan
yang berorientasi pasar ini pula yang membuat Unhas, sebagai salah satu
perguruan tinggi terbesar di kawasan Indonesia Timur, beberapa hari yang lalu
disahkan keberadaan statusnya sebagai PTN-BH oleh Kemenristek. Dengan Imajinasi
target sirkulasi modal yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan hingga 450
milyar. Dengan menjadikan pendidikan sebagai instititusi modal seperti ini,
pendidikan diharapkan bisa lebih adaptif terhadap tuntutan-tuntutan
pembangunan, begitu harapan Presiden. Dalam konteks ini paradigma pembangunan Jokowi,
bisa dibilang tidak berbeda jauh dari pendahulu-pendahulu sebelumnya, yakni
terciptanya suatu road map pendidikan
yang tanggap dan berorientasi deveplomentalisme.
Apa yang salah? Tentu saja kita akan mudah berkata
bahwa tidak ada yang salah dengan konsep ini. Mengingat kenyataan akan rendahnya kecakapan penguasaan
ilmu terapan di kalangan pelajar memang patut kita akui. Namun, tentu saja bahwa
ada beberapa hal mendasr yang mesti kita kritisi. Tentang bagimana menempatkan,
dan atau menjembatani antara kepentingan pendidikan itu sendiri dengan
kepentingan pasar itu sendiri. Kapitalisasi pendidikan memang seperti gunung
es, yang tampak indah di atas permukaan, namun kadang-kadang menyembunyikan
hal-hal lain yang berkontradiksi dengan itu semua.
Pendidikan, pasar dan kapitalisme
Jauh sebelum kita membicangkan
relasi pendidikan dan pasar hari ini. Karl Marx, sudah berbicara di masanya,
dua abad yang lalu. Marx bahkan memberi tanda, bahwa sekolah harus mendapatkan concern lebih ketimbang agama untuk
dianalisis. Meski kedua-duanya sangat syarat dengan kepentingan kelas. Sama-sama
bagi Marx bisa menjadi pranata untuk menanamkan kesadaran borjuis, tapi sekolah
memberikan kontribusi lebih dari itu semua. Sebab ia (sekolah) menyuplai
kontribusi praktis dan material dalam melanggengkan modus produksi kapitalisme.
Sebabnya dalam konteks ini, pendidikan menghasilkan kemampuan kerja. Kemampuan-kemampuan
yang ketika tidak dilakukan periodisasi ideologi, bisa dengan sendirinya
menjadi sekrup-sekrup pion dari sistem kapitalisme itu sendiri lewat mobilisasi
kelas sosial secara individual, melahirkan kelas menengah yang diuntungkan dari
keberadaan sekolah. Suatu kelas sosial yang menurut banyak orang, menjadi gambaran
dari wujud pengkaburan kelas-kelas sosial yang ada. Yang ikut melanggengkan surplus value lewat jabatan-jabatan
kerah putih yang ia miiki.
Menggunakan analisa Marxis untuk
meihat perkembangan sekolah hari ini, membuat kita sampai pada kesimpulan,
bahwa penguatan revitalisasi sekolah berbasiskan pasar dan penyediaan tenaga
kerja hari ini adalah wujud dari kemenangan kapitalisme dalam mengkooptasi
pendidikan. Ia (kapitalisme) bahkan tak perlu mengeluarkan biaya untuk sekadar bisa
mendapatkan tenaga kerja murah dan cuma-cuma siap pakai. Para orang tua pelajar
lah yang membayarkannya, bahkan tak sedikit dari kalangan orang tua-orang tua
proletarlah yang kembali mengongkosi siklus ini dengan membayar ongkos
pendidikan yang tak murah. Mereka-mereka para orang tua yang sudah diperas
habis-habisan di dalam pabrik oleh majikannya, namun juga kembali diperas oleh
sekolah/kampus yang tak lain adalah perpanjang tanganan kapitalisme itu sendiri.
Bahkan di tingkat sekolah menengah
kejuruan, para kapitalis-kapitalis tanpa merasa malu, berlomba-lomba
mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang masih di bawah umur (untuk kategori
pekerja) untuk dipekerjakan dengan cuma-cuma, atas nama tututan kurikulum
pendidikan? Ya, mereka-mereka siswa-siswa kita yang PKL (Praktik Kerja Lapangan),
atau mereka para mahasiswa yang melakukan KKN Industri. Dalam rentang masa
kerja yang dipersamakan dengan orang dewasa, para kapitalis menikmati pasokan
tenaga kerja sekolahan ini dengan cuma-cuma. Ada semacam sebuah persegongkolan
sadar antara pemerintah, sekolah dan modal yang terjadi di lingkaran ini,
menjerat sekolah tanpa daya kritis. Mereka-mereka tanpa rasa berdosa dengan
sendirinya melemparkan anak dalam ruang-ruang penyiksaan psikologis, beban
kerja ganda antara sekolah dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan industri yang ia
laui.
Apakah hal-hal ini, tak bisa kita
definisikan sebagai suatu kekerasan struktural dalam dunia pendidikan berbasis
pasar hari ini? Tentu saja kita mahfum,
bahwa toh, kapitalisme memang tak bisa jauh-juh dari hal-ihwal tentang
kekerasan. Jamil Salmi (1983) dalam bukunya Kekerasan
dan Kapitalisme (terj), bahkan menyebut kapitalisme berkembang dan bertahan
karena kekerasan. Ia membuktikan itu dengan meneliti pola-pola penyebaran
kapitalisme di dunia. Tak perlu jauh untuk memahami penelitian Jamil, cukup
kembali menegok di sekitar kita. Puncak kapitalisasi pendidikan Unhas kemarin
yang berujung kekerasan adalah contoh paling nyata di pelupuk mata, bahwa
kekerasan adalah alat paling sahih untuk menegakkan kapitalisme.
Alienasi dan kapitalisasi pengetahuan
Di perguruan-perguran tinggi,
inilah paling mengancam kita. Yakni kapitalisasi perguruan tinggi akan
benar-benar memisahkan kampus dengan persoalan hidup rakyat kecil. Harapan Soekarno
agar pendidikan yang ada tidak boleh
memunggungi persoalan rakyat menjadi termentahkan lewat kapitalisai perguruan
tinggi yang marak belakangan ini. Kapitalisasi pendidikan, ujung-ujungnya
menciptakan privatisasi dan kapitalisasi pengetahuan, yang akhirnya membuat rakyat
kecil teralienasi dari keberadaan kampus-kampus. Logika pendidikan yang
diharuskan untuk adaptif terhadap pembangunan adalah logika kapitalisasi
pendidikan itu sendiri yang diperhalus.
Dengan semangat mengedepankan
parodi/jurusan teknik seperti arahan Presiden, disertai dengan semangat
pengkapitalisasian pendidikan. Persekutuan pendidikan dan dunia industri
menemukan momentum perkawinannya yang pas. Jadi, jangan heran dan terkatup-katup,
ketika kita lebih mudah mendapati para intelektual kampus lebih sibuk
melegitimasi reklamasi atau pendirian pabrik semen, di banding berpihak pada
petani, nelayan dan rakyat kecil. Jangan heran, ketika penelitian-penelitian
mahasiswanya lebih banyak diarahkan berorientasi pada upaya menemukan dan
mengembangkan produk-produk yang bisabersinergi dengan korporasi-korporasi,
ketimbang mengangkat tema-tema persoalan yang menjerat rakyat kecil. Ini adalah
kenyataan-kenyataan yang kita saksikan sekaligus menunggu di depan mata.
Ini adalah salah satu konsekensi
dari kampus yang resmi berorientasi diri sebagai institusi modal. Ia harus secara
terus menerus harus memandang bahwa aktivitas keilmuan sebagai sebuah komoditi
untuk mencapai target pendapatan kampus yang milyaran itu. Sehingga benarlah
kata orang, bahwa penemuan itu pada dasarnya ideal pada tataran teori, tapi ia
menjadi bisnis pada tataran praktik. Sebab kita berhadapan dengan kenyataan
bahwa produk intelektual menjadi perkara bisnis. Benar kata Marx dalam Robin
Small (2014--terj.), bahwa kemajuan
secara umum dan akumulasi pengetahuan masyarakat (dalam konteks ini—pen.) dikuasai
dengan gratis oleh kapital.
Kondisi lain yang menjadi dampak
dari ini semua adalah kembalinya persoalan pendidikan kita pada ranah klasik,
yakni ketimpangan distribusi ilmu pengetahuan yang tidak adil. Dikarenakan bahwa
kapital telah mengkooptasi pendidikan terlebih dahulu, maka bentuk peminggiran
terhadap rakyat kecil akan terus terjadi. Ini adalah proses pemborjuisan
lembaga pendiidkan. Tidak hanya akan mengasingkan rakyat kecil untuk mengakses
pendidikan, juga pada tataran cakupan keilmuan, dominasi sudut pandang keilmuan
akan menyesaki kesadaran pelajarnya dengan satu sudut pandang penuh batasan. Kooptasi
tentu saja tidak hanya berada dalam ambang batas akses terhadap pendidikan yang
timpang, namun juga pada batasan-batasan keilmuan yang harus sesuai dengan kepentingan
kapital.
Inilah resiko, sekaligus
pergeseran fatal yang bakal terjadi ketika pendidikan benar-benar tumbuh
sebagai institusi modal. Dimana moralitas-moralitas beserta segenap kesadaran
yang menyertainya tak lain merupakan moralitas pasar semata. Ia benar-benar
akan membunuh segala bentuk jalan dari munculnya kesadaran-kesadaran kritis
yang bertentangan dengan kepentingan pasar. Dan tidak berlebihan ketika kita
benar-benar mengatakan bahwa pendidikan dalam konteks seperti ini telah dibunuh,
dibunuh perlahan-perlahan lewat kooptasi kesadaran pasar?
Apa yang hilang dari sekolah teknik kita?
Ketika pendidikan berjalan sebagai
institusi modal, maka itu artinya telah terjadi pengkurusan kenyataan
pendidikan sebagai institusi ideologi. Dan inilah yang terjadi. Pembukaan SMK
ataupun jurusan-jurusan teknik di perguruan tinggi, hampir dipastikan bahwa ia
lahir semata-mata sebagai jawaban atas tuntutan pasar semata, bukan tuntutan
ideologi. Karena itu agak sulit untuk bisa melihat para lulusan sekolah teknik
kita bisa lahir dengan kepribadian seperti Soekarno misalnya yang juga seorang
insinyur teknik. Pun ketika ada hanya sedikit, ketimbang produk-produk
pendidikan dengan kesadaran pasar yang pure.
Sekolah teknik kita, hanya mentok
bisa melahirkan ‘tukang’. Tukang dalam arti sekadar pekerja yang kering dengan
konsepsi-konsepsi ideologi. Paling banter kita temukan adalah kenyataan
ketidakmampuan untuk membangun keterhubungan antara ilmu teknik yang mereka
kuasai dengan hal-hal yang bersifat ideologis lainnya. Inilah yang pernah
disebut Marx sebagai bentuk pemutusan kesadaran ideologis. Dalam pandangan Marx,
bahwa seorang individu yang terspesialisasi dan terdidik secara sempit akan
menjadi seseorang yang terputus dari seluruh umat manusia. Dan ini sangat mudah
kita temui, seorang sarjana teknik atau lulusan sekolah yang tidak mampu menemukan
keterkaitan antara keilmuan dan tugasnya sebagai seorang manusia.
Maka tidak heran ketika, kita
melihat seorang sarjana teknik, bisa membangun gedung-gedung tinggi, sembari
menggusur ladang dan rumah rakyat-rakyat kecil, tanpa sedikitpun merasa
berdosa. Mereka-mereka para pekerja teknik ini, lulusan sekolah dan perguruan
tinggi pasar hanya melihat bangunan dengan teras dan besi yang kuat sebagai
pencapaian keilmuan, tanpa menganggap bahwa membangun dengan menginjak manusia
lain sebagai persoalan yang terkait dengn keilmuan mereka. Sebagian mungkin
abai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahkan yang paling memalukan dari
itu semua, adalah mereka yang justru lahir dengan kredo, menganggap bahwa menggusur
untuk mebangun adalah keharusan. Ini yang paling gila! Ini sama gilanya ketika
seorang sarjana pertanian, lebih pro pabrik baja dan pabrik semen ketimbang sawah
dan perkebunan.
Apa yang menyebabkan itu semua?
Lagi-lagi, pengetahuan yang berkembang, di tengah pendidikan yang telah terindustrialisasi
oleh kepentingan pasar, akan mudah kita lihat kemana pengetahuan itu berpihak. Modal
telah mensekulerkan kita dari persoalan-persoalan ideologi dalam ranah
pendidikan. Ia benar-benar merenggutnya. Sama halnya yang terjadi terhadap
agama. Kita selalu berkata bahwa komunis itu anti-agama, tapi kita lupa
menganalisis bahwa yang membunuh agama sejak lahirnya adalah kapitalisme itu
sendiri, menggantinya dengan imaji-imaji kekuasaan modal.
Saya sendiri, percaya bahwa kita
butuh sekolah teknik. Tapi pertanyaannya, sekolah teknik yang mana? Sekolah teknik
yang berpihak kepada siapa?
Disni saya teringat dengan
analisis Rendra beberapa tahun silam dalam sebuah wawancara di media sebelum
kepergian beliau. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ia mengurai persoalan
substansi pendidikan kita yang melompat mengikuti ritme desain pendidikan
kolonial. Saat Belanda menjajah nenek moyang kita, ilmu-ilmu yang diperkenalkan
Belanda memang hanyalah ilmu-ilmu teknik. Tentu saja yang seturut dengan kepentingan
belanda itu sendiri. Ada dua kepentingan Belanda, kenapa Belanda lebih memilih
memperkenalkan ilmu teknik di sekolah-sekolah yang mereka ampuh saat itu. Yakni pertama, untuk mendapatkan tenaga
kerja murah dalam mendukung pembangunan dan eksploitasi gula dan pabrik-pabrik
mereka (kepentingan pasar mereka). Yang kedua,
untuk menghalau muncul dan berkembangnya ilmu-ilmu humaniora dan sosial, yang
bisa mengancam keberadaan mereka sebagai bangsa penajajah. Singkatnya, ilmu
teknik diperkenalkan untuk itu.
Apa konsekuensi dari perkembangan
pendidikan dengan desain seperti itu, yang diwarisi sekarang ini? Itu tadi,
kembali lagi kepada persoalan sebelumnya. Lahirnya produk pendidikan yang mentok
bermental pekerja toh saja, yang sama sekali tidak mengerti persoalan masyarakatnya.
Atau bahasa lainnya intelektual-intelektual teknik yang tak memiliki keterkaitan
kemanusiaan dengan masyarakatnya (terasing dari kehidupan kemanusiaannya
sendiri). Karena itu tidak heran ketika produk-produk teknik dari pendidikan kita
memang mengarah pada kepentingan pasar bukan kepentingan masayarakat. Dalam arti
kita dijejalkan dengan pengetahuan teknik untuk mencipta tanpa didasari oleh
landasan ideologi sosial yang kuat. Kita mencipta tidak dilandasi oleh riset
tentang kebutuhan rakyat, melainkan disetting terlebih dalam pada
kebutuhan-kebutuhan koorporasi.
Ilmu-ilmu sosial yang seharusnya
bisa bersinergi dengan ilmu teknik justru dipisahkan menjauh dari kesadaran
keilmuan kita. Seolah-olah mengafirmasi kenyataan bahwa ilmu teknik itu ya
untuk teknik, tidak ada keterkaitan dengan persoalan sosial masyarakat. Di sekolah
menengah kejuruan saja, ilmu sosiologi sebagai ilmu sosial dasar pun tidak ada
dalam kurikulum. Saya tidak tahu apakah ini bentuk keblingeran atau apa?
Kembali lagi ke pernyataan
sebelumnya. Saya sendiri, percaya bahwa kita butuh sekolah teknik. Tapi pertanyaannya
selanjutnya, sekolah teknik yang mana? Sekolah teknik yang berpihak kepada
siapa?
Penulis
Muhammad Ruslan