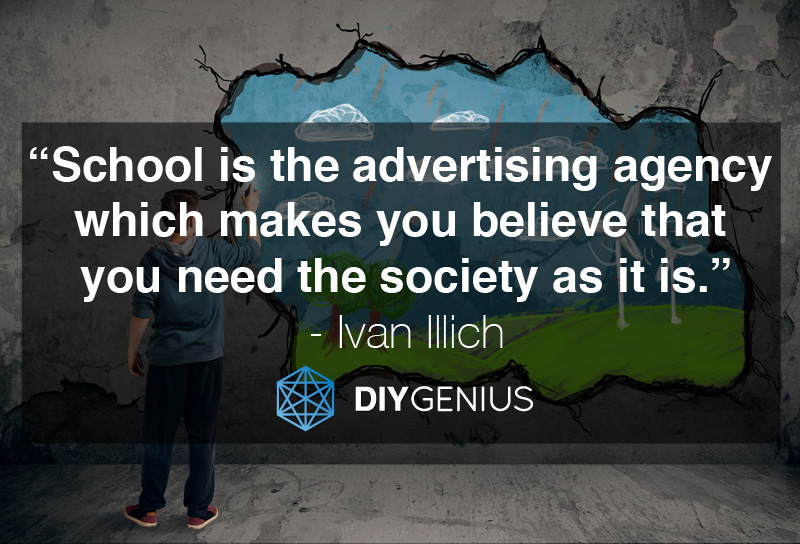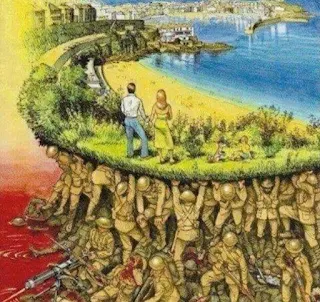 |
| source picture: google |
Habis gelap terbitlah terang, setelah terang terbitlah
kembali gelap!
Saya mengenal Kartini, sebagai seorang pejuang perempuan
yang pernah dimiliki bangsa ini. Gagasan-gagasannya menjadi cermin, sekaligus
dijadikan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia untuk ikut mendobrak dan
melabrak tatanan sosial yang menindas perempuan. Tapi, Song Ji Hyo, sama sekali
saya tidak mengenalnya, selain tahu dari namanya sebagai artis Korea, setelah
mencarinya di internet.
Kartini tenar di masa pra kemerdekaan, beberapa windu yang
lalu, ia seperti api yang menerangi. Pikiran-pikirannya hinggap di benak,
mengganggu pikiran bangsa saat itu. Tapi itu dulu! Sekarang, berbeda, Kartini
sudah seperti simbol peradaban kuno masa lampau, sedang Song Ji Hyo adalah
simbol modernitas zaman terkini. Dalam benak muda-mudi, apalah artinya Kartini di
zaman Song Ji Hyo? Kartini hanya menjdi nama jalan, dalam imajinasi yang ada
hanya Song Ji Hyo. Kok bisa? Ya itulah realitasnya!
Beberapa menit yang lalu, saya singkapkan waktu untuk
menengok mading, salah satu sekolah, berharap mendapatkan informasi menarik,
atau setidaknya ingin melihat dinamika kepenulisan di sekolah bersangkutan. Tapi
sungguh mencengangkan, isinya semua berisi profil dan lika-liku artis KOREA! Dari
laki-laki hingga perempuan—penuh gambar dengan
gaya necisnya yang khas!
Ini seperti ekspresi gejala hedonisme yang menumpuk dalam
imajinasi pelajar, seperti terwadahi dalam ruang sekolah. Sekolah/kampus, tidak
mapu mengambil peran counter, hanya
karena counter terhadap ide-ide
‘modernitas’ mungkin dianggap sebagai hal yang kolot, seperti kolotnya orang
yang melawan arus modernitas itu sendiri. Definisi tentang kemajuan, menjadi
sarat dengan nilai-nilai hedonisme.
Kita seperti tak berdaya untuk merepersepsi ide-ide tentang
modernitas itu, sekolah dengan banyaknya plus-plusnya itu, mulai berbentuk Boarding School, plus kurikulum international, dll, tidak mampu menghadirkan
budaya intelektual yang kritis, selain sekadar ‘menyemai’ dan melayani budaya
global yang dominan, yang sama sekali tidak mengandung dimensi intelektualitasnya
yang berpihak pada nilai. Kurikulum yang semakin mengglobal tersebut, seperti
semakin mengasingkan kehidupan sekolah terhadap nilai-nilai lokalitas, yang
justru semakin mendekatkannnya dengan kultur hedon global.
Jangan tanya di sekolah ataupun kampus sekalipun, biografi Tan
Malaka, Kartini, Soekarno dikenal baik, apalagi berharap gagasan-gagan tokoh
tersebut dikenal. Tak pernah terjadi ada “deman Tan Malaka” atau “deman Kartini”
melanda para pelajar, selain tiap hari bergelut dengan “deman Korea”.
Korea? Apa yang ia tahu tentang Korea, selain kehidupan para
artisnya, sikap hedon para artis, sama sekali ia tidak tau dinamika politik
korea hingga hari ini. Sehingga imajinasi tentang yang idealpun di mata pelajar
adalah idea-idea seperti yang terlukis dalam sinetron Korea yang hedon. Mereka
akan menatap hidup dengan cara seperti itu, sibuk dengan insting dan hal remeh-temeh,
seolah-olah hidup hanya terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan
semata! Dalam romantisme artifisial, ia terbuai pemahaman dangkal tentang arti
cinta.
Pertanyaannya, Apa yang kita harapkan di masa depan atas
generasi masa depan yang asing terhadap gagasan
Kartini, Tan Malaka, Soekarno, saat imajinasi dipenuhi dengan pola pikir
hidup hedon semata? Suatu imajinasi palsu yang disetting di atas
kesepaktan-kesepakatan bisnis lewat media, dihembuskan untuk diterima, di atas
ladang subur, yakni kesadaran paling polos, kesadaran para pelajar yang belum
mengerti banyak tentang kehidupan. Dengan satu tujuan, menciptakan kesadaran
materialistik terhadap kehidupan ‘manusia’ itu sendiri.
Dalam imajinasi palsu disemai, pabrik media lewat
eksploitasi diri sang artis, terus menerus memanen pundi-pundi kapital,
menyisakan anak-anak muda/mudi yang terhisap secara kesadaran, kurus secara
imajinasi akibat tereksploitasi sejak dini.
Para pelajar ini, semakin teralienasi dengan kehidupan nyata
itu sendiri, ide-ide dipenuhi dengan hal- hal mengambang yang sama sekali tak
memiliki pijakan pada kehidupan. Beberapa bulan silam, seorang pelajar meminta
pendapat/saran saya secara kosep atas film pendek yang sementara ia gagas. Sebelum
saya berpendapat, terlebih dahulu saya meminta mereka menjelaskan konsep yang
ia miliki, dan isinya: penuh dengan imajinasi romantisme kekanak-kanakan, tak
satupun hal yang saya dapatkan bahwa ide-ide itu mewakili kehidupan yang
sesungguhnya.
Apakah itu belum cukup menjadi tanda, bahwa, sekolah betul-betul
mengasingkan pelajarnya pada kehidupan yang sebenarnya? Imajinasi yang menjadi
ide, betul-betul terpisah dari kenyataan!
Dan fenomena apa pula yang terjadi, saat pelajara-pelajaran
tentang Soekarno dibahas dalam ruang belajar, tapi keluar dengan imajinasi
idola sang artis hedon? Tugas-tugas profil Kartini dibuat di atas lembar kusam,
pulang dengan tempelan foto Song Ji Hyo di kamar penuh, hingga di buku-buku? Lantas
apa arti dari pelajaran-pelajaran akan tokoh tersebut bagi pelajar?
Tak heran, ketika para pelajar lebih gandrung dan lebih banyak
mengenal artis Korea, ketimbang tokoh-tokoh bangsa maupun tokoh dunia yang banyak
memiliki sumbangsih kemanusian bagi kehidupan. Realitas sekolah tidak mampu
mengkondisikan kesadaran penokohan itu terhadap pelajar.
Fenomena “Habis gelap terbitlah terang, hingga kembalilah
gelap” menjadi karang kehidupan pelajar, ditengah sekolah yang kehilangan daya
sebagai pranata budaya. Potret Kartini semakin asing dalam benak para
penerusnya. Saat Kartini memproklamirkan wacana otonomi tubuh perempuan dan
kesetaraan perempuan yang bermartabat, sekarang penerus Kartini semakin terbuai
dengan Song Ji hyo, simbol komersialisasi tubuh dan pemameran ‘kelemahan’
perempuan di hadapan laki-laki atas nama cinta sesat dan romantisme materialistik.
Budaya patriarkar menyusup lewat kesadaran terdalam, secara hegemonik disemai
dan diterima secara pasif. Sebuah simulacra
‘egalitarinisme ruang publik hedon’ yang materialistik, diperrealitaskan!
Muhammad Ruslan