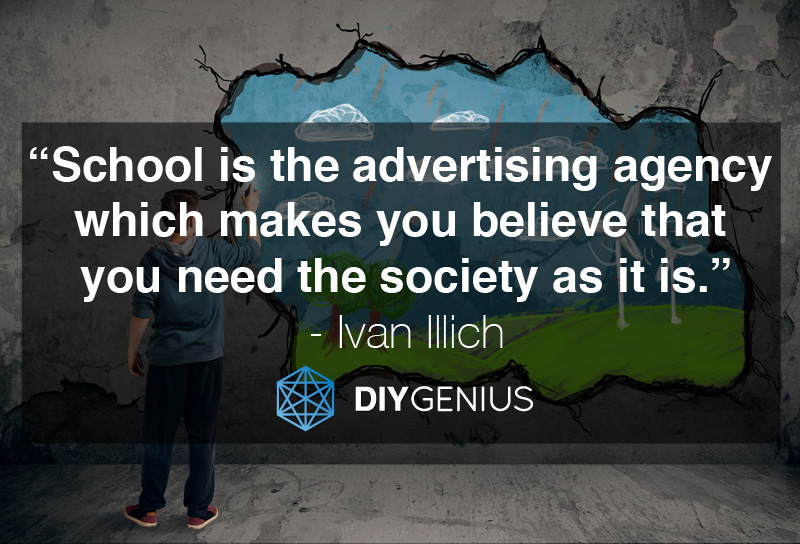|
| sources: google |
Kampung Walang (Ancol, Jakarta
Utara), tempat Sekolah Darurat Kartini (SDK) berdiri. Kampung yang yang seolah hidup
dalam kematian, dan mati dalam kehidupan. Hidup pun tak mau mati pun tak segan.
Tak pula ia disebut ‘’anak tiri’’. Pasalnya, dari ratusan warga yang hidup
selama bertahun-tahun, keberadaan RT dan RW yang merupakan simbol pengakuan
eksistensi pemukiman belum ada. Kekhawatiran akan penggusuran selalu menghantui
penghuninya.
Dari arah jalan raya, tepat di bawah
jalan tol, tak tampak tanda untuk dapat menyebutnya pemukiman. Hanya tumpukan
materil yang mengisi ruang bawah jalan tol. Dari tumpukan pasir, kerikil,
tumpukan kayu bekas, besi bekas, kardus bekas, koran hingga plastik bekas
berjejer layaknya pagar, seolah menyembunyikan keberadaan bahwa ada kehidupan
yang berlangsung di dalamnya. Kehidupan yang enggan untuk dijamah otoritas. Mereka para yang termarginalkan, yang
terus hidup dalam kekhawatiran akan penertiban kota.
Hanya petak-petak kecil yang
tersekati dinding seng, sebagian tripleks
yang beratap beton jalan tol untuk dapat menyebutnya sebagai rumah.
Ketika masuk, hanya empat meter, barulah tampak bahwa lokasi tersebut adalah pemukiman.
Beberapa anak tampak berlalu-lalang, bermain dengan genangan air di jalan-jalan
setapak. Riuh suara anak kadang-kadang tenggelam ketika kereta yang hanya
berkisar lima meter dari arah permukiman lewat dengan bunyinya yang nyaring.
Kampung ini berada dalam jepitan antara jalan raya dan rel kereta api.
Sekolah
darurat
Di permukiman inilah, berdiri
sekolah darurat, yang menyandang nama Sekolah Darurat Kartini. Dengan luas
sekolah yang hanya berkisar 9X6 meter, dilebur dalam satu ruangan. Sekolah ini
rela berbagi kesempitan ruang dengan warga, setelah enam kali berpindah tempat,
terusir atas alasan penertiban kota. Dari tempat ke tempat lain, sekolah ini
terus bertahan, berkat asuhan pendirinya, Sri Irianingsih dan Sri Rosyati, yang
dikenal ‘’Ibu Kembar’’, hingga akhirnya sejak 2013 yang lalu baru mendapat
pengakuan.
‘’Ini satu-satunya sekolah yang
kami miliki sejak puluhan tahun kami tinggal disini. Seperti halnya rumah kami,
kami menolak digusur,’’ ucap D, Kepala Kelompok Masyarakat Kampung Walang Blok B,
Sabtu (17/1).
Meskipun D mengakui bahwa tanah
yang ia pijati bersama warganya (termasuk sekolah) berada dalam kewenangan PT
KAI (Kereta Api Indonesia), dan Jasa Marga (pengelola jalan tol). Ia tetap tak
berharap mimpi buruknya akan penggusuran terjadi ke depannya, seperti yang
terjadi diberbagai tempat di Jakarta.
Bertahan
dalam keterbatasan
Meski hidup dalam keterbatasan,
sekolah ini memiliki murid ratusan dari berbagai kampung yang ada disekitarnya.
Hal tersebut menurut penuturan R (37),
warga yang bermukim di depan sekolah, yang anaknya mengenyam pendidikan di sekolah
tersebut.
‘’Disini gratis, tidak ada biaya,
makan pun gratis. Kadang-kadang juga diberi susu tiap-tiap rumah. Tiap hari
sekolah, ibu kembar selalu memasakkan anak-anak makanan,’’ ujar B (53), warga
Kampung Walang.
Terlihat di dalam ruangan
setumpuk bahan makanan dalam bungkusan kardus mi bertumpuk di sudut ruangan. Di
depan pintu juga terlihat alat-alat masak seperti panci, dan kuali. Dan
alat-alat makan seperti piring dan gelas. Di bagian belakang ruangan terdapat
tiga buah tungku yang terbuat dari tanah liat, tempat untuk memasak dengan
menggunakan kayu bakar.
Kursi yang bertumpuk sekitar 70
unit, dan meja sekitar 35 unit, tampaknya tak mencukupi untuk menampung jumlah
murid. ‘’Tiap hari, sebagian siswanya belajar di luar (pekarangan, dekat pinggir
jalan), pakai tikar,’’ ujar T (29), ibu dari Ta (4), salah seorang siswa TK di
sekolah tersebut.
Menurut T, hanya ‘’Ibu Kembar’’ yang menjadi
guru utama yang mengajar semua murid. Sedangkan yang membantunya adalah siswanya
sendiri yang sudah di atas tingkat. ‘’Kalau TK
dan SD biasanya diajar sama yang SMP atau SMA,’’ ujarnya. Penulis
Muhammad Ruslan
*tulisan ini (setelah disesuaikan kembali), mentahnya ditulis Januari 2015, hasil pengalaman belajar jurnalistik (penulis) di salah satu media cetak. tulisan tidak diterbitkan di media manapun, dan diterbitkan disini untuk tujuan pendidikan.
**nama narasumber dirubah dalam bentuk inisial