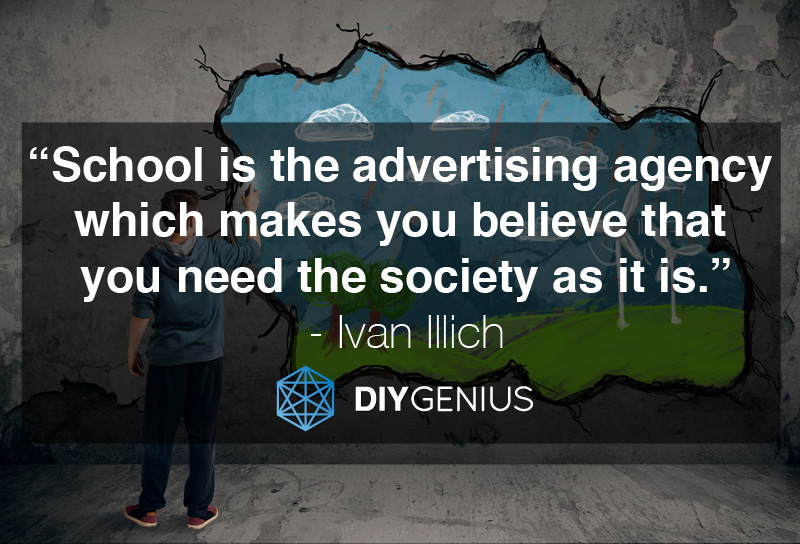Kalau di media sosial muncul
sarkasme yangmengatakan orang Indonesia kearab-araban, sedangkan Arab kebarat-baratan,
maka dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita juga memperlihatkan siklus
terbalik. Ilmu pengetahuan kita menjadi kebarat-baratan saat yang sama Barat justru
diam-diam mempelajari ketimuran.
Gagasan back to nature ala JJ Roessau,
atau gagasan pensejajaran fisika modern dan mistisisme ketimuran dari Fritjof
Chapra memperlihatkan dinamika perkembangan pengetahuan Barat yang berputar itu.
Upaya menggali dan kembali membongkar naskah-naskah kuno ketimuran yang selama
ini diabaikan, seperti menemukan kembali apa yang hilang bagi mereka. Apa yang
mereka sebut takhayul dan mitos-mitos ketimuran itu justru diam-diam dikaji
kembali. Chapra bahkan menyebut fenomena ini sebagai titik balik peradaban.
Sedang apa yang terjadi di Timur,
Indonesia khususnya? Kita seperti baru saja terasa mengakhiri masa merangkak
menjadi baligh. Baru saja memamah masa gelap kita sembari mengutuk segala
bentuk apa yang kita definisikan sebagai mitos sebagai sesuatu yang kolot, yang
tak lain dalah peradaban nenek moyang kita sendiri. Sembari mengalihkan pandang
pada peradaban Barat yang gemilang karena pencapaian akal dan segenap
antroposentrisme pengetahuannya yang maskulin. Teknologi yang diciptakan Barat semakin
membuat kredo ketakjuban kita menjadi-jadi.
Gagasan-gagasan yang pernah
mengguncang pencapaian peradaban Barat dua hingga tiga abad lampau, baru saja
menghampiri kita. Sekularisasi dan positivisme pengetahuan seperti sebuah sabda
bagi orang timur sekarang ini. Ia seperti bodhi,
kredo jalan dari perkembangan adopsi corak pengetahuan Barat yang
diinteranalisasi dalam berbagai perangkat intitusi pendidikan kita hari ini.
Sangat mudah mengidentifikasi hal
ini. Generasi-generasi tua yang masih mendominasi aktivitas kampus hari ini
masih menjadi pertanda bahwa tradisi keilmuan abad ke-18 ini, masih menguasai
lalu-lintas intelektual kita sekarang ini. Bagi Anda yang masih berkutat dengan
aktivitas kampus, sangat mudah merasakan atmosfer ini. Khususnya saat ingin
penelitian, dan mendapatkan pembimbing yang tua-tua. Hehe (meskipun tidak
semunya).
Terlebih lagi di lingkup
pendidikan dasar hingga menengah. Bidang ekonomi misalnya, coba kita lihat teori-teori
ekonomi yang diajarkan sampai hari ini misalnya. Teori-teori ekonomi yang sudah
seharusnya kadarluarsa, namun masih terus direproduksi saat ini tanpa pernah
direvisi, apalagi dikritisi. Dari jaman nenek moyang keturunan XVI sampai
sekarang. Yang diajarkan sebagai pokok dasar persoalan ekonomi hanyalah itu-itu
saja: What, How dan Whom. Ini tak lain merupakan masalah pokok
ekonomi paling klasik, yang muncul saat pertama kali meletus revolusi industri.
Saat manusia masih kebingungan dalam memanfaatkan teknologi industri untuk
kepentingan pasar. Antara apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya hingga
pertanyaan untuk siapa barang itu diproduksi.
Tak jauh berbeda ketika misalnya
teori-teori ekonomi abad ke-18 ini masih menjadikan isu kelangkaan karena
faktor alam sebagai simpul pokok persoalan ekonomi. Isu-isu kelangkaan yang didefinisikan
dalam persepktif akumulasi modal dan eksploitasi alam. Kelangkaan barang yang
mengharuskan manusia mendekati persoalan ekonomi lewat penigkatan produksi
secara massif, yang berarti eksploitasi, akumulasi, dan surplus value.
Padahal, saat ini kita justru berhadapan dengan suatu persoalan ekonomi yang terbalik 180 derajat dari konsepsi itu semua. Bukan tentang kelangkaan yang kadang menjadi persoalan ekonomi, tapi justru sebaliknya, kita berhadapan dengan fenomena overproduksi. Overproduksi yang berpangkal pada eksploitasi alam dan buruh yang sangat cepat akibat teknologi yang tak terkontrol. Namun, Overprduksi ini selain telah berhasil membuat sebagian kecil manusia kekenyangan, namun justru tetap membuat sebagian besar manusia yang lain tetap kelaparan. Ada apa? Justru hal-hal ini tidak pernah dikonsepsi sebagai persoalan ekonomi.
Padahal, saat ini kita justru berhadapan dengan suatu persoalan ekonomi yang terbalik 180 derajat dari konsepsi itu semua. Bukan tentang kelangkaan yang kadang menjadi persoalan ekonomi, tapi justru sebaliknya, kita berhadapan dengan fenomena overproduksi. Overproduksi yang berpangkal pada eksploitasi alam dan buruh yang sangat cepat akibat teknologi yang tak terkontrol. Namun, Overprduksi ini selain telah berhasil membuat sebagian kecil manusia kekenyangan, namun justru tetap membuat sebagian besar manusia yang lain tetap kelaparan. Ada apa? Justru hal-hal ini tidak pernah dikonsepsi sebagai persoalan ekonomi.
Begitupun halnya, bahwa persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini tidak lagi sekadar berhulu pada persoalan produksi semata. Kita berhadapan dengan persoalan ekonomi yang kompleks dari hulu ke hilir. Dari produksi, hingga distribusi dan konsumsi. Persoalan distribusi adalah persoaan ketimpangan dan ketidakadilan dalam mengakses sumber daya ekonomi, yang melahirkan kejahatan struktural berupa pemiskinan dan penghancuran ekologis.
Alih-alih ingin mengatasi kelangkaan dengan produksi, kita justru mengalami suatu proses penambalan masalah ‘kecil’ menuju masalah yang lebih besar. Seperti kata Illich, kita mengatasi kelangkaan relatif menuju kelangkaan absolut. Masa depan sumber daya alam dengan karkater yang tidak mudah diperbarui itu terancam punah terlebih dahulu ketimbang bisa memenuhi kebutuhan manusia jangka panjang.
Peningkatan konsumsi akan modal, tenaga kerja, sumber daya alam untuk kepentingan produksi, justru pada kenyataannya tidak membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Atas nama efisiensi dan logika akumulatif, barang-barang justru sengaja diproduksi dengan kualitas yang rendah. Untuk tetap bisa mempertahankan siklus akumulasi modal kapitalisme bertahan. Dampaknya cukup serius, akumulasi laba meningkat tajam, konsumsi meningkat drastis, namun angka harapan hidup rakyat kecil semakin mengenaskan. Dan apakah semua hal-hal ini telah disbutitusikan sebagai persoalan pokok ekonomi sekarang ini?
Saat ini, di Barat sendiri, perkembangan pemikiran dan paradigma pengetahuan sudah jauh melampaui apa yang justru terus menerus menjadi objek pengetahuan kita saat ini. Paradigma antorposentrisme dan positivisme pengetahuan yang menjadi corak pengetahuan pasca Rennaisans justru dianggap sebagai biang keladi persoalan kemanusiaan yang inheren melanda peradaban Barat itu sendiri. Krisis sosial yang terjadi, dan krisis ekologi yang mengguncang Barat, adalah ekses dari paradigma pengetahuan yang mndewakan manusia dengan segenap kekuasaan pasar yang ada. Kapitalisme benar-benar menampakkan wajahnya dengan vulgar dengan segala bentuk kekejaman dan penindasan yang menyertainya.
Sebagai kritik akan realitas itu,
di Barat sendiri ada banyak paradigma-paradimga pengetahuan yang muncul dengan karakternya yang holistik. Salah satunya
adalah paradigma pengetahuan hijau, yang mencoba merangkul sisi-sisi
ekologis, spritualitas alam dan sosial dalam melakukan rekonsepsi ulang terhadap ilmu pengetahuan.
Lebih dikenal dengan istilah ekonomi hijau. Misalnya, dengan mensubtitusi
faktor-faktor lain dalam merumuskan ulang pendefinisian-pendefinisian tentang
ukuran-ukuran kesejahteraan dalam ranah kualitas, dengan melibatkan
faktor-faktor alam dan manusianya. Dll.
Penguatan paradigma hijau, bahkan
tidak hanya menginspirasi lahirnya rekonstruksi teoritis pada berbagai ranah
pengetahuan, tapi juga di ranah praktis. Ia bahkan muncul sebagai sebuah
paradigma gerakan, seperti dengan munculnya partai-partai politik progressif
yang menamakan diri partai hijau (termasuk di Indonesia).
Saat ini, kita sebenarnya bisa dikatakan
mengalami dua persoalan serius dalam melihat dinamika perkembangan pemikiran
yang ada saat ini. Yang pertama adalah pentaglikan berlebihan kita terhadap
produk pengetahuan Barat yang membuat kita kehilangan sikap kritis dan unsur
kreativitas dalam mencipta pengetahuan sendiri. Membuat tidak hanya produk
duplikasi pengetahuan tetapi juga dengan segenap dampak-dampaknya. Dalam konteks
ini, saya teringat salah satu sajak Rendra yang berkata: “Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing | tekad-tekad hanya
boleh membeli metode | tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan | kita
mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa |menghayati sendiri semua
persoalan yang nyata”.
Persoalan yang kedua adalah
sebagian justru berlindung di balik segala fundamentalisme doktrin anti-asing,
kembali ke lokalitas, namun justru gagap dalam melakukan reinterpretasi atas
kebudayaan lama. Akibatnya gagasan-gagasan yang ada hanya bisa membeku,
diterima layaknya mantra suci penuh dogma. Kegagalan dalam melakukan
rasionalisai dan sinkronisasi kemajuan terhadap segala bentuk kebudayaan lama
yang membuat kita stagnan.
Dan yang paling ironis dari itu
semua, adalah bahwa kita dilanda stagnasi intelektual yang akut. Agama dengan
segala bentuk penafsiran konservatis atasnya justru seringkali menjadi penyebab
dari menjamurnya kesadaran-kesdaran fatalisme berpengetahuan. Akibatnya disksursus-diskursus
pengetahuan tidak pernah berkembang dengan dinamis dan serius.
Alih-alih untuk bisa memikirkan diskursus pengetahuan alternatif,
kita lebih memilih melemparkan diri ke dalam klise fatalisme-fatalisme moral. Ini
sangat mudah diidentifikasi, saat lembaga-lembaga pendidikan yang ada misalnya,
lebih dominan menjadi polisi moral ketimbang upaya untuk membangun dan
membangkitkan kesadaran kritis pelajar.
Sepertinya deman agama dan gila
moralitas yang melanda lembaga pendidikan kita saat ini, mengingatkan saya pada
gila agama yang melanda Eropa di abad-abad kegelapan (dark age) dua/tiga abad yang lampau. Gila agama yang muncul dengan
wajah dogma yang anti terhadap segala bentuk pengetahuan yang tidak bersumber dari
(penafsiran otoritas agama) terhadap kitab-kitab suci. Dan itu menjangkiti
tidak hanya lembaga agama, tapi juga lembaga-lembaga pengetahuan yang ada saat
itu.
Dan saya merasa kenyataan-kenyataan
ini pun hingga akirnya terbawa di masyarakat. Apa yang paling terus menerus
membuat kita ribut akhir-akhir ini? Diskurus pengetahuan baru? Bukan. Isunya selalu
berputar pada hal-hal itu saja. Agama! dengan segala bentuk penafsiran
konservatisme atasnya.
Penulis
Muhammad
Ruslan