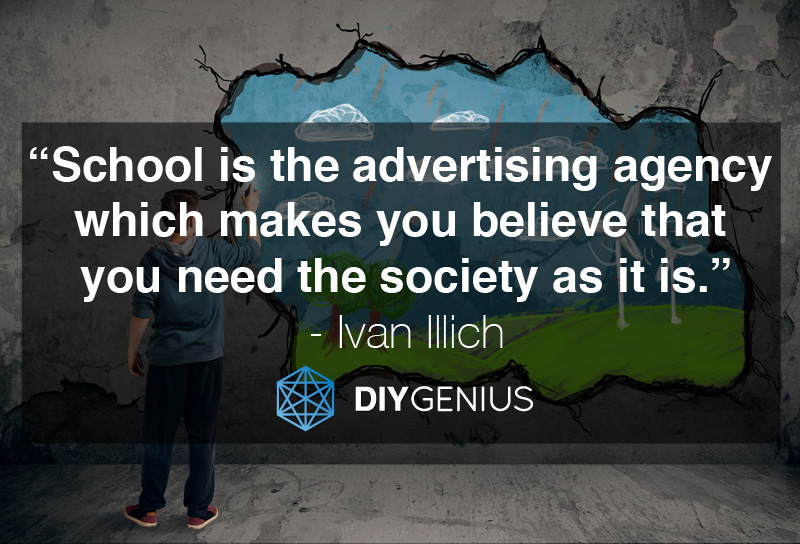|
| sumber gambar:
|
Radikalisasi agama yang marak terjadi belakangan ini, tentu
membuat kita semua prihatin. Sebab radikalisasi ini tidak mengarah pada semagat
militansi agama dalam menjawab persoalan sosial dan menubuhkan kesalehan
sosial, tetapi sebaliknya justru mengarah pada semangat fundamentalisme yang
sektarian. Penghakiman-penghakiman sepihak karena perbedaan pikiran, pendapat, agama
maupun madzhab, hingga beberapa di antaranya berujung kekerasan.
Tahun yang lalu pembakaran masjid dan pembakaran gereja
cukup menyita perhatian, belum kasus diusir dan dibakarnya perkampungan warga Syiah
di Sampang. Melihat lebih belakang lagi hanya membuat kita semakin miris. Setali
dengan hal itu, tindakan-tindakan intimidasi dan penutupan paksa diskusi hingga
warung makan, bahkan pengusiran Ibu Sinta, Istri Almarhum Gusdur, lusa (17/6)
tak luput dari seperangkat ironi intoleransi yang terjadi. Kejadian-kejadian
ini semuanya berakar dari satu persoalan yakni: model keberagamaan yang
fundamentalis anti-kemajemukan, melanda seperti penyakit (pseudo beragama). Ini adalah suatu ironi intoleransi yang selau
berpotensi menyulut tragedi.
Bagi siapapun – termasuk
penulis – yang terbiasa berinteraksi lintas agama, akan merasakan atmosfer
kekesalan yang terpendam. Ruang-ruang sosial yang sedianya sudah seharusnya
mencair justru selalu saja ada pihak yang menginginkannya membeku dalam suatu
kotak-kotak simbolitas keberagamaan. Hal ini hanya justru berkontribusi dalam
memupuk ketidakharmonisan dalam bermasyarakat.
Dalam tulisan ini, saya hanya ingin melihat skop lingkup
persoalan ini dari sudut padang pendidikan. Dan mencoba melihat isu
fundamentalisme dalam skop yang lebih luas
dari sekadar agama. Dengan menarik suatu hipotesa bahwa pendidikan yang ada
saat ini ikut berkontribusi dalam menyuplai energi bagi lahirnya semangat fundamentalisme
dan menyemai benih intoleransi sejak dalam pikiran. Kenapa bisa?
Karl Henrich Marx, atau lebih lazim dikenal Marx, pernah
mengatakan bahwa keseluruhan persoalan-persoalan ‘agama’ yang ada saat ini
(saat itu, yang masih relevan dengan kekinian), haruslah dilihat sebagai
persoalan-persoalan sosial itu sendiri. Itu berarti persoalan agama khususnya
yang berpangkal pada isu sektarian ini, berakar pada persoalan sosial struktur
yang ada. Tak terkecuali dalam hal ini adalah pendidikan sebagai salah satu
elemen dari struktur sosial yang dimaksud. Meski pendidikan bukanlah penyebab
primer, tetapi secara tidak langsung kultur pendidikan yang ada saat ini ikut
andil untuk hal itu.
Pengkotak-kotakan
sekolah
Kondisi kultur persekolahan yang terkotak-kotak oleh
semangat primordialisme suku dan simbolitas agama saat ini ikut bertanggung
jawab. Saat ini kita tidak sulit untuk melihat banyaknya sekolah yang
bermunculan dengan ciri dan simbolitas kelompoknya yang khas. Baik simbolitas
itu bersumber dari semangat kesukuan, agama, bahkan semangat madzhab sekalipun.
Terlalu langka untuk melihat adanya sekolah yang betul-betul lahir dari cara
padang majemuk melihat realitas majemuk sebagi sesuatu yang ideal.
Saat ini kita hanya melihat dan mendorong isu persekolahan
dalam kerangka keramahan sekolah terhadap anak/pelajar, agar ruang kekerasan fisik
tidak terjadi. Tetapi masih meninggalkan hal lain, yakni keramahan sekolah
terhadap perbedaan horizontal. Masih terlalu langka untuk melihat sekolah yang
benar-benar lahir dari cara pandang majemuk. Sekolah yang ada justru
dikondisikan dengan wataknya yang eksklusif.
Ada sekolah berbasis agama A, B, C, bahkan adapula sekolah
dengan basis agama tapi khusus untuk madzhab tertentu saja. Selain itu,
terdapat pula sekolah yang terlalu elitis untuk golongan tertentu saja, bahkan
sekolah yang ‘dihuni’ oleh suku tertentu pun ada.
Secara hukum tak ada yang salah dengan hal itu. Tapi secara
sosial, kita mencoba meraba bahwa produk-produk sekolah yang lahir dari
keterasingan berinteraksi secara majemuk akan membawa potensi-potensi lain, tak
terkecuali bagi tersemainya kesadaran anti-kemajemukan. Secara politik
pendidikan, desain sekolah yang seperti di atas, sebenarnya bertentangan dengan
visi kemajemukan yang harus dirajut.
Semangat ketertutupan sekolah justru disemai. Padahal keberbauran
itulah yang seharusnya dipupuk. Keberbauran bisa menangkal segala bentuk gejala
radikalisme bersuku dan beragama secara sektarian.
Saya pikir, tindakan sektarian yang lahir dari cara berpikir
dogmatis, yang mengganggap diri dan keyakinannyalah paling benar atau mungkin
satu-satunya yang benar di dunia, lahir bukan karena kurang piknik, atau kurang
beribadah, tetapi karena kurangnya bergaul lintas agama. Semua orang memang
lahir berpotensi terradikalisasikan oleh dogma agama, saya yakin dengan
pergaulan akan membuka ruang kita untuk berpikir terbuka, hingga menemukan dan
menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kebaikan itu sangat universal. Kebaikan
lahir dan muncul dari kalangan siapa saja, seperti halnya dengan keburukan itu
sendiri.
Karena itu, para pengusung gerakan lintas iman atau lintas
agama, sangat menekankan keterbukaan itu dan dialog sebagai salah satu
alternatif dalam meredam isu sektarian ini. Dan ironisnya ketika sekolah yang
justru seharusnya menjadi pranata sosial paling depan untuk membuka ruang itu,
justru keburu terkena penyakit fundamen ketertutupan. Terlalu mudah melihat
sekolah dengan karakter yang sangat eksklusif. Bahkan pengalaman penulis,
pernah ditolak oleh salah satu sekolah agama, hanya karena saya berasal dari
organisasi keagamaan yang dikenal sangat moderat (hehe).
Ini menjadi ironi yang cenderung diabaikan dalam kultur persekolahan
yang ada. Salah seorang cendekiawan muslim, Cak Nur sudah memperkenalkan konsep
keberagamaan inklusif ini, ide yang dikaji dari kondisi sosial masyarakat kita,
sebenarnya telah mengingatkan kita akan hal itu. Hanya saja sepertinya kita
terlambat untuk menindaklanjutinya di tingkat operasional sekolah.
Membiarkan pengkotak-kotakan dengan semangat ketertutupan
yang ada dalam kultur persekolahan yang ada saat ini, sama halnya dengan
mengkondisikan benih-benih fundamentalisme dan intoleransi tumbuh di lahan yang
subur. Saat sekolah yang seharusnya berperan mencairkan perbedaan-perbedaan
sosial yang ada, justru ikut mengungkung perbedaan-perbedaan itu dalam
sangkar-sangkar simbolitas yang sempit.
Ketertutupan hanya akan melahirkan streotipe, rasa curiga
yang terus berangsur-angsur, hingga terlalu mudah dipolitisir, hingga berpotensi
meledak dalam gesekan-gesekan horiozntal. Dan hal itu sudah sering kita alami
sejak zaman kolonial hingga sekarang. Bahwa ketertutupan memudahkan segala
bentuk kepentingan bisa menyulut konflik. Kita dengan mudah bisa berkaca pada
kebijakan politik deivide et impera
kolonial Belanda beberapa ratus tahun silam. Kebijakan pengkotak-kotakan dalam
dunia pendidikan memang diciptakan untuk memangkal isu-isu solidaritas,
persatuan dan sejenisnya.
Apalagi saat ini,
ketika negara justru ikut dalam proses pengkotak-kotakan sekolah itu. Sebagian
sekolah di bawah kendali Kementerian Pendidikan, sebagian pula di bawah kendali
Kementerian Agama. Ini seperti pemerintah juga gagal untuk mensinkronkan antara
pembelahan itu dengan kurikulum 2013 yang ia susun sendiri yang menekankan
keterpaduan. Belum lagi, perbedaan sekolah antara negeri dan swasta yang justru
melahirkan pembedaan perlakuan pemerintah. Ini menjadi sebuah contoh dari wajah
ganda perlakuan negara, serupa dengan kasus-kasus intoleransi yang ada: yang
justru lebih banyak mengamankan korban daripada menghukum pelaku.
Kurikulum pendidikan
agama yang memalukan
Bukan hanya kualitas buku-buku sekolah yang kadang-kadang
memalukan, tapi juga kurikulumnya. Di tingkat sekolah menengah misalnya,
pelajaran-pelajaran agama sepertinya tidak pernah naik ke kelas yang lebih
tinggi. Pelajaran agama diajarkan dibangku sekolah menegah, tidak ada bedanya
dengan yang diajarkan dibangku menengah pertama dan sekolah dasar. Seolah-olah
agama itu terlalu sempit untuk dibahas, dan pembahasannya seolah-olah hanya itu-itu
saja. Agama dalam konteks ini diajarkan sebagai hal yang teknis semata, seperti
tata cara beribadah, tata cara berdoa, dll.
Pelajaran agama hanya menjadi seperangkat paket doa-doa yang
dijarkan secara dogmatis. Doa-doa yang harus dihafal dan dilafalakan seperti
mantra untuk mendapatkan nilai praktik. Padahal kalau kita merujuk gagasan Bapak
Pendidikan -- Ki Hadjar Dewantara -- misalnya,
sudah seharusya pendidikan agama di tingkat menengah haruslah menyesuaikan
dengan tuntutan kodrat perkembangan psikologi dan kedewasaan pelajar.
Kalau saja pendidikan kita saat ini diframing dari
kondisi-kondisi sosial masyarakat, maka seyogyanya pendidikan agama yang ada
seharusnya membincangkan persoalan-persoalan intoleransi dan radikalisasi agama
yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti kata Ki Hadjar Dewantara: sistim
pengajaran haruslah berfaedah, lahir dari kehidupan dan penghidupan sosial masyarakat,
untuk kepentingan berbangsa!
Seyogyanya pendidikan agama ditingkat sekolah menengah
memang haruslah berpradigma lebih luas dari sekadar pengteknikalisasian agama
semata. Mengingat kondisi pikiran pelajar sudah memenuhi syarat untuk
membincangkan agama dengan pendekatan yang lebih universal. Pemerintah khususnya
lewat kementerian agama, harus mengambil tupoksi yang lebih besar akan hal ini:
meramu pelajaran agama yang terpadu secara universal. Mengingat bahwa menangkal
radikalisasi agama bukanlah proyek jangka pendek, melainkan jangka panjang
karena terkait dengan pikiran manusia. Sebab pseudo beragama anti-kemajemukan ini, bukanlah suatu kenyataan
insenditil dan personal, tetapi sebuah persoalan sosial yang mendaur lewat alam
pikiran: mewarisi dan diwarisi yang berpotensi beranak-pinak lewat proses sosial
pendidikan itu sendiri.
Melihat banyaknya kejadian
konflik sektarian yang pernah terjadi dalam catatan gelap sejarah bangsa
kita ini hingga terus terjadi saat ini pun, baik yang berkarakter suku maupun
agama, sudah seharusnya mendorong kita memikirkan bahwa virus anti-kamajemukan
itu tidak terwarisi ke generasi selanjutnya. Proses waris mewarisi ini memang
lebih tepat dan seharusnya dipikul oleh pranata pendidikan. Oleh karenanya, menciptakan
suatu kultur pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap kemajemukan adalah
tantangan pendidikan kita ke depannya!
Penulis
Muhammad Ruslan