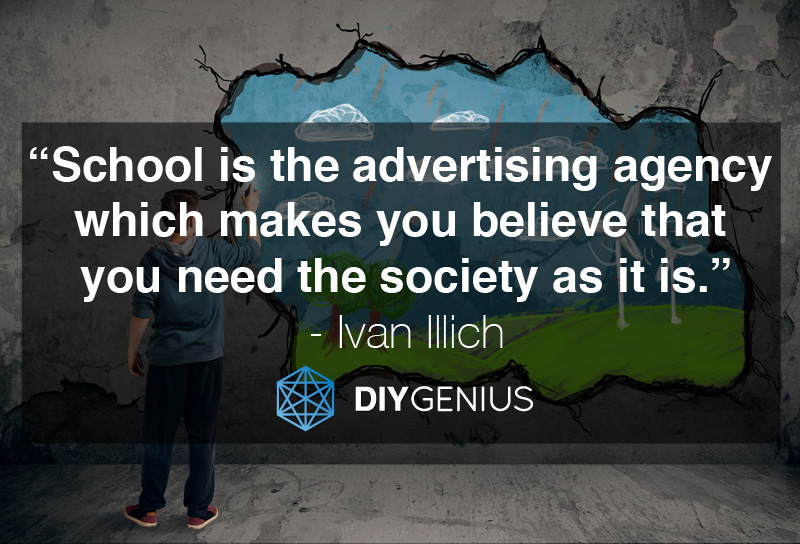Refleksi atas perjalanan pendidikan kita hingga hari ini membawa kita pada simpul pokok persoalan. Yakni pada peredabatan-perdebatan konsepsional dan paradigmatik akan kemana pendidikan harus berdaras. Konsepsi yang ada kemudian terlihat seperti berjalan pincang karena ketidakmampuan untuk meramu hal-hal yang cenderung bertentangan dalam satu konsepsi utuh. Yang kemudian pada akhirnya hanya melahirkan produk pendidikan dengan karakter ganda. Personalitas ganda yang lahir akibat ketidakjelasan konsepsi utuh yang teramu.
Ilmu yang ada misalnya tidak mampu menyentuh sisi terintim kemanusiaan, akibat terbentur di titik dasar kenaluriaan. Dalam arti bahwa pendidikan tidak mampu mendamaikan titik-titik pragmatisme dan altruisme manusia. Sistem persekolahan yang ada saat ini lebih dominan hanya mampu memantik kesadaran naluri manusia ketimbang kesadaran terintim ia sebagai manusia dengan segenap realitas kemanusiaannya yang dalam. Kesadaran-kesadaran yang diproduksi hanya mentok pada kesadaran pasar, dengan segenap pragmatisme dan individualisme yang angkuh.
Apa yang menjadi gambaran ideal tentang bayangan masa depan dalam benak pelajar misalnya selain masa depan yang penuh akumulasi materialistik. Hal itu lahir sebagai hasil konstruksi dari sistem dan arah pendidikan yang berjalan. Pendidikan yang mahal, dan sistem pendidikan yang menuankan materi secara berangsur-angsur muncul secara rill, secara tidak langsung mengajari pelajar dalam suatu kesadaran tertinggi tentang tujuan hidup yang materialistik dan pragmatis. Sangat sering saya mendengar ungkapan klasik dari pelajar berkata: “Uang yang orang tua keluarkan untuk sekolah sudah sangat banyak, masa nanti cuma digaji seperti buruh?”.
Di masa muda seperti inilah anak didik hidup dalam pola pikir timbal balik. Doktrin-doktrin bahwa pendidikan adalah investasi untuk mendatangakan materi dalam logika bisnis mengisi ruang idealisme yang terlanjur dibiarkan kosong. Pandangan-pandangan kesadaran yang memilah dan mendiskreditkan manusia berdasarkan indikator-indikator materialistik, yang pada akhirnya memisahkan ia dari persoalan-persoalan kemanusiaan. Sungguh ironis. Ilmu yang ada ternyata tidak cukup mampu menubuhkan kesadaran-kesadaran sosial yang membebaskan, justru sebaliknya . Pendidikan seperti ini hanya menciptakan cara pandang yang mendiskreditkan manusia, bukannya memantik suatu empati akan khendak untuk membebaskan manusia. Teringat kata Tan Malaka: “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” .
Dalam konteks ini lantas kita bertanya: Apa guna pendidikan?, kalau toh kesadaran tertinggi yang ia sajikan hanyalah kesadaran naluri seperti ini? Untuk berpikir tentang akumulasi, materialistik, dan segenap kebahagiaan individu yang dikejar, saya rasa tak perlu dengan pendidikan, kehidupan ini sudah cukup untuk membangkitkan pragmatisme seperti ini. Sama halnya kalau kita bilang: Tak perlu ada seseorang yangmengajari kita tentang keburukan dan penderitaan, kehidupan ini sudah cukup menyajikan hal itu!
Kesadaran materialistik, mencari kebahagiaan individu semata, asosialis, yang memenuhi kepala pelajar bukan karena pilihan mereka dalam keadaaan sadar, melainkan hasil konstruksi dari sistem pendidikan dan sistem persekolahan yang menjadi akar persoalan. Sekolah dan segena p sistem pendidikan yang ada saat ini bertanggung jawab akan hal ini. Saya begitu mudah melihat bagaimana aturan sekolah itu diframing dari ide-ide materialistik seperti ini. Bukan hanya iuran sekoah yang mahal, biaya masuk, biaya pembangunan (yang tak ada habisnya), dan sejenisnya, bahkan banyak sekolah yang menetapkan aturan sanksi dalam bentuk denda (uang) bagi siswanya yang melanggar.
Sanksi sekolah dalam bentuk denda (sejumlah uang) ini, menurut saya adalah salah satu praktik purba yang mengandung absurditas nilai yang fatal dalam sekolah. Selain bias kelas, dalam arti mendiskreditkan siswa dalam kelas-kelas sosial, model ini juga secara tidak langsung menfatwakan seolah-olah bahwa hukum itu bisa dibeli: Dengan mengeluarkan segopoh uang, maka orang bisa terbebas dari sanksi hukum.
Karena itu kembali lagi, sistem seperti itulah yang harus bertanggung jawab dalam mengalienasikan manusia dari sifat kemanusiaan terintim yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sistem yang hanya bisa membangkitkan kesadaran yang membentur naluri. Dalam konteks lebih luas wacana pendidikan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang menginginkan penghapusan sekolah gratis, justru semakin menebalkan pesimisme akan nasib pendidikan kita yang semakin materialistik dan menindas ini. Atas nama partisipasi dan logika “gotong royong” yang diwawacanakan Menteri Muhadjir, terkandung logika pasar yang mendiskreditkan hakikat pendidikan dan tanggung jawab negara terhadp pencerdasan kehidupan bangsa itu sendiri.
Pragmatisme yang melanda produk pendidikan kita hingga hari ini seharusnya dipandang sebagai sebuah persoalan yang serius. Apakah karena pendidikan kita yang berjalan ini memang terlalu lemah untuk bisa diframing dalam satu settingan ideologis? Sehingga kemudian begitu mudahnya pragmatisme dan materialisme ini mengisi relung kesadaran produknya? Dalam konteks ini persoalan pendidikan memang harus kembali mempertanyakan hal-hal mendasar: “Kemana pendidikan ini akan mengarah?”. Apakah ingin maju menemukan formula kemanusiaan baru terhadap pendidikan, ataukah justru mundur mengangkangi kemanusiaan itu sendiri? Dengan segenap pengteknikalisasian dan industrialisasi pendidikan yang terus dijajalkan sebagai konsep ‘baru’.
Untuk sampai kesana, tidak tepat ketika pendidikan hanya terus dipandang sebagai sebuah pranata birokratis semata. Pendidikan haruslah berlepas diri dari cara pandang birokratis yang mengungkungnya. Memandang pendidikan dalam kerangka birokratis hanya melahirkan konsepsi-konsepsi permukaan, yang sekadar memandang pendidikan sebagai suatu proses formal, namun justru di titik inilah persoalaan-persolan manusiawi dalam pendidikan justru terus terdiskreditkan. Yang pada akhirnya konsep wacana yang ditawarkan hanya mampu berhasil memantik riak pro-kontra, hingga akhirnya berlalu begitu saja. Seperti pada wacana full day school sebelumnya.
Penulis
Muhammad Ruslan
Repost: dari: http://www.kompasiana.com/2220/materialitas-pendidikan-yang-mendiskreditkan-kemanusiaan_57c5b8b4bd22bd8c5219c5eb
Ilmu yang ada misalnya tidak mampu menyentuh sisi terintim kemanusiaan, akibat terbentur di titik dasar kenaluriaan. Dalam arti bahwa pendidikan tidak mampu mendamaikan titik-titik pragmatisme dan altruisme manusia. Sistem persekolahan yang ada saat ini lebih dominan hanya mampu memantik kesadaran naluri manusia ketimbang kesadaran terintim ia sebagai manusia dengan segenap realitas kemanusiaannya yang dalam. Kesadaran-kesadaran yang diproduksi hanya mentok pada kesadaran pasar, dengan segenap pragmatisme dan individualisme yang angkuh.
Apa yang menjadi gambaran ideal tentang bayangan masa depan dalam benak pelajar misalnya selain masa depan yang penuh akumulasi materialistik. Hal itu lahir sebagai hasil konstruksi dari sistem dan arah pendidikan yang berjalan. Pendidikan yang mahal, dan sistem pendidikan yang menuankan materi secara berangsur-angsur muncul secara rill, secara tidak langsung mengajari pelajar dalam suatu kesadaran tertinggi tentang tujuan hidup yang materialistik dan pragmatis. Sangat sering saya mendengar ungkapan klasik dari pelajar berkata: “Uang yang orang tua keluarkan untuk sekolah sudah sangat banyak, masa nanti cuma digaji seperti buruh?”.
Di masa muda seperti inilah anak didik hidup dalam pola pikir timbal balik. Doktrin-doktrin bahwa pendidikan adalah investasi untuk mendatangakan materi dalam logika bisnis mengisi ruang idealisme yang terlanjur dibiarkan kosong. Pandangan-pandangan kesadaran yang memilah dan mendiskreditkan manusia berdasarkan indikator-indikator materialistik, yang pada akhirnya memisahkan ia dari persoalan-persoalan kemanusiaan. Sungguh ironis. Ilmu yang ada ternyata tidak cukup mampu menubuhkan kesadaran-kesadaran sosial yang membebaskan, justru sebaliknya . Pendidikan seperti ini hanya menciptakan cara pandang yang mendiskreditkan manusia, bukannya memantik suatu empati akan khendak untuk membebaskan manusia. Teringat kata Tan Malaka: “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” .
Dalam konteks ini lantas kita bertanya: Apa guna pendidikan?, kalau toh kesadaran tertinggi yang ia sajikan hanyalah kesadaran naluri seperti ini? Untuk berpikir tentang akumulasi, materialistik, dan segenap kebahagiaan individu yang dikejar, saya rasa tak perlu dengan pendidikan, kehidupan ini sudah cukup untuk membangkitkan pragmatisme seperti ini. Sama halnya kalau kita bilang: Tak perlu ada seseorang yangmengajari kita tentang keburukan dan penderitaan, kehidupan ini sudah cukup menyajikan hal itu!
Kesadaran materialistik, mencari kebahagiaan individu semata, asosialis, yang memenuhi kepala pelajar bukan karena pilihan mereka dalam keadaaan sadar, melainkan hasil konstruksi dari sistem pendidikan dan sistem persekolahan yang menjadi akar persoalan. Sekolah dan segena p sistem pendidikan yang ada saat ini bertanggung jawab akan hal ini. Saya begitu mudah melihat bagaimana aturan sekolah itu diframing dari ide-ide materialistik seperti ini. Bukan hanya iuran sekoah yang mahal, biaya masuk, biaya pembangunan (yang tak ada habisnya), dan sejenisnya, bahkan banyak sekolah yang menetapkan aturan sanksi dalam bentuk denda (uang) bagi siswanya yang melanggar.
Sanksi sekolah dalam bentuk denda (sejumlah uang) ini, menurut saya adalah salah satu praktik purba yang mengandung absurditas nilai yang fatal dalam sekolah. Selain bias kelas, dalam arti mendiskreditkan siswa dalam kelas-kelas sosial, model ini juga secara tidak langsung menfatwakan seolah-olah bahwa hukum itu bisa dibeli: Dengan mengeluarkan segopoh uang, maka orang bisa terbebas dari sanksi hukum.
Karena itu kembali lagi, sistem seperti itulah yang harus bertanggung jawab dalam mengalienasikan manusia dari sifat kemanusiaan terintim yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sistem yang hanya bisa membangkitkan kesadaran yang membentur naluri. Dalam konteks lebih luas wacana pendidikan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang menginginkan penghapusan sekolah gratis, justru semakin menebalkan pesimisme akan nasib pendidikan kita yang semakin materialistik dan menindas ini. Atas nama partisipasi dan logika “gotong royong” yang diwawacanakan Menteri Muhadjir, terkandung logika pasar yang mendiskreditkan hakikat pendidikan dan tanggung jawab negara terhadp pencerdasan kehidupan bangsa itu sendiri.
Pragmatisme yang melanda produk pendidikan kita hingga hari ini seharusnya dipandang sebagai sebuah persoalan yang serius. Apakah karena pendidikan kita yang berjalan ini memang terlalu lemah untuk bisa diframing dalam satu settingan ideologis? Sehingga kemudian begitu mudahnya pragmatisme dan materialisme ini mengisi relung kesadaran produknya? Dalam konteks ini persoalan pendidikan memang harus kembali mempertanyakan hal-hal mendasar: “Kemana pendidikan ini akan mengarah?”. Apakah ingin maju menemukan formula kemanusiaan baru terhadap pendidikan, ataukah justru mundur mengangkangi kemanusiaan itu sendiri? Dengan segenap pengteknikalisasian dan industrialisasi pendidikan yang terus dijajalkan sebagai konsep ‘baru’.
Untuk sampai kesana, tidak tepat ketika pendidikan hanya terus dipandang sebagai sebuah pranata birokratis semata. Pendidikan haruslah berlepas diri dari cara pandang birokratis yang mengungkungnya. Memandang pendidikan dalam kerangka birokratis hanya melahirkan konsepsi-konsepsi permukaan, yang sekadar memandang pendidikan sebagai suatu proses formal, namun justru di titik inilah persoalaan-persolan manusiawi dalam pendidikan justru terus terdiskreditkan. Yang pada akhirnya konsep wacana yang ditawarkan hanya mampu berhasil memantik riak pro-kontra, hingga akhirnya berlalu begitu saja. Seperti pada wacana full day school sebelumnya.
Penulis
Muhammad Ruslan
Repost: dari: http://www.kompasiana.com/2220/materialitas-pendidikan-yang-mendiskreditkan-kemanusiaan_57c5b8b4bd22bd8c5219c5eb