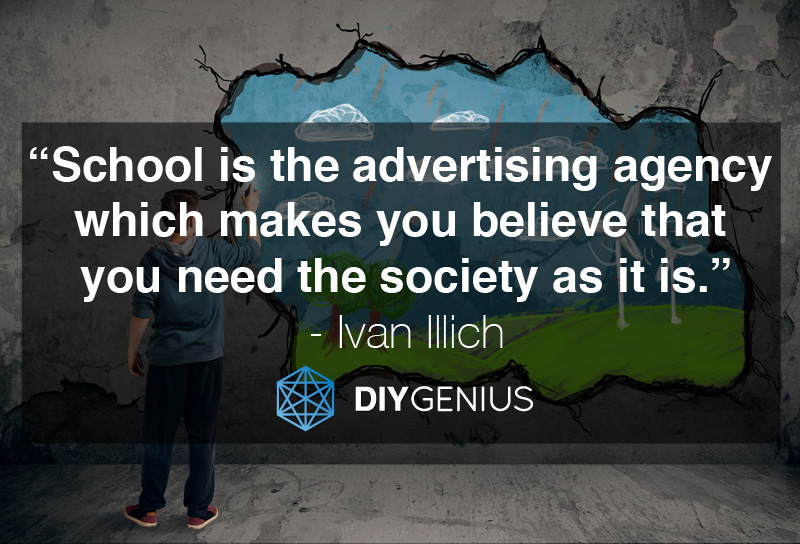Tulisan ini
saya buat, sebagai reaksi dari diskusi yang baru saja saya ikuti di Maitreya. Sebagai
peserta diskusi, di tengah banyaknya
peserta yang lain yang harus menyampaikan pendapatnya pula, ditambah ketertabasan
waktu, membuat saya tidak bisa mengutarakan secara ‘utuh’ pendapat pribadi
saya. Karena itu tulisan ini berusaha untuk menindaklanjuti hal itu. Rencananya semoga beberapa hari ini saya bisa
menurunkan tulisan yang berententan terkait hal ini: dua atau tiga tulisan
terkait, mengingat pokok substansi pembahasan yang cukup luas dan menuntut
kedalaman. Setidaknya saya menyebut ini sebagai bentuk ‘keberhasilan’ diskusi kemarin,
karena setidaknya bisa memancing saya (sebagai peserta diskusi) untuk membuat
tanggapan lebih lanjut atasnya.
Di sesi ini,
saya hanya ingin fokus menggambarkan aliran-aliran paradigma dasar yang hingga
hari ini berkembang sebagai wacana sekaligus alat analisis dalam melihat persoalan-persoalan
pendidikan yang mencuat. Pembahasan akan hal ini berusaha semaksimal mungkin
untuk tidak mengelaborasi secara terlalu teoritis, namun berusaha untuk mengkonkretisasinya
dari persoalan-persoalan keseharian yang terjadi di dunia pendidikan yang kita
alami sehari-hari.
Selain itu,
keinginan saya untuk membahas paradigma dasar ini, tiada lain karena suatu hal
yang menggangggu pikiran saya selepas diskusi kemarin. Salah satunya adalah,
kekhawatiran saya atas pendapat-pendapat saya yang cenderung “liar” berpotensi
disalahpahami. Kedua, menginginkan agar pernyataan-pernyataan saya atas diskusi
ditempatkan sebagai pendapat pribadi semata, yang tidak menuntut sebuah
afirmasi ‘benar atau salah’, melainkan lebih ke ‘sepakat atau tidak sepakat’
semata. Ketiga, selain keterbatasan waktu yang ada, tidak detailnya penjelasan saya
juga dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat personal. Titik penjelasan saya
yang berorientasi kritik struktural berpotensi melahirkan ‘ketersinggungan’, saya
mahfum bahwa “tidak selamanya kita akan terus merasa baik-baik saja atas kritik”.
Meskipun saya yakin akan kedewasaan kita bersama, bisa menempatkan kritik dengan elegan (semoga!).
Dan yang
kelima, kenapa ini penting untuk dibahas, adalah saya melihat, lewat
penafsiran-penafsiran pribadi saya, saya dan kita melihat masih terpola secara
reaksioner terhadap persoalan pendidikan yang mencuat. “Persoalan ada dan
solusi ada”, kurang lebih seperti itu, dan karena hal itu pula kita mengabaikan
hal-hal yang bersifat history atasnya. Ketika saya terus menempatkan persoalan
pendidikan di ruang hampa, yang saya persepsi kehadirannya ada begitu saja, dan
menafikan hal di luar dari persoalan itu sendiri. Karena itu ide-ide segenap
solusi yang ada kadang-kadang bersifat instan idealistik, yang hanya membuat saya
lebih mudah membuat solusi ketimbang memahami dengan utuh (persoalan-persoalan
yang ada).
Atau lebih
tepatnya, yang saya ingin katakan, bahwa membincangkan persoalan pendidikan
yang ada, ada baiknya ketika kita merujuk hal-hal itu pada dimensi perdebatan substansial:
yakni menggiringnya pada perdebatan-peredabatan epsitemologis dan ontologis. Saya
dan kita, bisa dikata mengabaikan hal-hal substansial itu, akibatnya tidak ada struktur
alur yang bisa membantu kita memahami persoalan pendidikan dengan lebih terang
dan mendasar. Karena itu, tulisan ini akan berusaha memulai kembali diskusi
tentang bagaimana persoalan-persoalan pendidikan yang kita bahas ditinjau dari
sudut pandang perdebatan-perdebatan aliran pemikiran pendidikan yang ada,
dengan harapan setidaknya kita bisa mengidentifikasi diri dalam aliran-aliran
pemikiran pendidikan yang ada. Berharap hal itu bisa membantu, saya lebih
khususnya, agar lebih jernih untuk melihat persoalan pendidikan yang kita alami
sehari-hari dengan pendekatan-pendekatan yang holistik, terhindar dari ambigu
dan kontradiksi-kontradiksi konseptual yang ada.
Kontradiksi dan
ambigu ini sangat nampak dalam banyak hal (kebijakan). Nilai yang dianggap
ideal masih terjebak dalam standar ganda penggunaannya, sehingga antar struktur
tidak terjadi alur irama yang sama, justru kadang-kadang bertentangan. Misalnya
saja antara metode pembelajaran dan sistem ujian. Terlalu nampak kontrakdiksi
itu terjadi. Metode pembelajaran yang mengarah ke hal-hal demokratis justru
berbenturan dengan sistem penilaian yang sangat feodal. Metode pembelajaran
yang menekankan kemajemukan berpendapat, analisa, penalaran-penalaran
subjektif, non-standardisasi, justru sistem penilaian (misalnya ujian yang ada)
masih bertahan dengan pola struktur yang lama seperti pilihan ganda, dsbnya,
yang dengan jelas mengebiri nilai-nilai yang ingin dikembangkan dalam metode
pembelajaran sebelumnya. Sehingga yang terlihat justru kontradiksi, yang secara
struktur menutup potensi dikembangkannya model pembelajaran demokratis itu
sendiri.
Dan banyak
lagi ---- tulisan-tulisan kedepannya akan
berusaha mengarah pada proses mengidenfikasi dan membongkar ruang nilai untuk
mempertanyakan struktur-struktur yang lama. Satu hal yang pasti, bahwa,
sistem yang ideal haruslah lahir dan terbebas dari kontradiksi-kontradiksi yang
ada.
Paradigma (aliran) dalam
pendidikan
Secara umum,
sedikitnya dalam tulisan ini, saya hanya membagi tiga paradigma dalam
pendidikan. Karena itu, kita lebih tepat menyebutnya paradigma dasar. Di antaranya:
paradigma konservatif, paradigma liberal, dan paradigma kritis.
Menjabarkan secara
singkat tiga paradigma di atas, bukanlah sesuatu yang harus dilihat dalam
kerangka absolut vertikal: benar-salah, atau sempurna-tidak sempurna, tapi
sekali lagi lebih bijak melihatnya dalam kerangka relativitas: yang mana kita
sepakati dan yang tidak kita sepakati, dan yang lebih idealistik lagi ketika
kita mampu mengafirmasi dan melakukan telaah kritik atas tiga konsep tersebut.
Meskipun
dalam pembahasannya, penekanan-penekanan tertentu baik yang bersifat kritik
ataupun hal-hal yang sifatnya keberpihakan, tidak lepas dari keterikatan
penulis dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Dalam konteks ini kita tentu
memahami bahwa tidak ada hal yang bebas nilai, tidak ada hal yang terlepas dari
subjektivitas, dan tidak ada hal yang sterill dari keberpihakan-keberpihakan,
pun tak terkecuali dengan penulis sendiri dalam membahasnya.
Tiga paradigma
di atas, lahir dan berkembang sebenarnya tidak lepas dari realitas sosio
pendidikan yang dinamis. Satu paradigma baru lahir adalah reaksi dari paradigma
yang lama, begitu seterusnya. Pendekatan dialektik memahamkan bahwa setiap kelahiran
konsep baru sebagai tesa, selalu ‘menuntut’ embrio bagi lahirnya antitesa, yang
berdialeketik dalam mendorong lahirnya sintesa-sintesa baru. Dari konteks itu,
kita mencoba memahami secara linear tiga paradigma di atas: konservatif,
liberal, dan kritis. Meski dipahami secara linear, bukan berarti ia terlepas
dari hal-hal dialektis atasnya, tak pula ia berarti hilangnya realitas yang
lama atas kelahiran yang baru. Keberadaaanya ada dalam di saat yang sama dalam
perdebatan-perdebatan konseptual dengan corak dan karakternya yang khas. Begitupun
bahwa menempatkannnya secara linear, bukan pula bermakna bahwa yang baru lebih
popular dari yang lama, dsbnya.
Paradigma konservatisme
Paradigma konservatif
ini, bagi saya adalah paradigma yang paling purba. Pada titik tertentu
paradigma ini cenderung anti terhadap segala hal yang baru. Ia mengandaikan
perubahan sebagai sebuah ancaman. Dalam konteks pendidikan, paradigma ini
mengasumsikan persoalan-persoalan pendidikan yang ada karena pengaruh dari
perubahan itu sendiri. Apa yang dianggap ideal adalah mempertahankan realitas
sebagai tradisi, memurnikan pendidikan dari pengaruh yang bisa mengancam
tradisi pendidikan yang sudah ada. Karakter paradigma ini sangat feodal: mempertahankan
nilai-nilai lama, berorientasi masa lalu bukan masa depan.
Kita sangat
mudah melihat guru dengan pengaruh paradigma ini (dengan sadar atau tidak),
khususnya pada guru yang dilahirkan dari tatanan lama, namun hidup dengan
segenap “kutukan-kutukannya” di tatanan baru. Mulai isu-isu anti Barat, liberal
dan sebagainya diproduksi sebagai sebuah wacana untuk menolak pengaruh, dan
kukuh bertahan dengan tradisi yang sudah ada, meskipun tradisi itu kadang-kadang
sudah bertahun-tahun ---- berabad-abad,
malahan.
Misalnya dalam
konteks hubungan guru-murid, paradigma konservatif akan menolak ide-ide
kesetaraan guru-murid. Bagi mereka sudah dan memang seharusnya tatanan hubungan
guru-murid itu bersifat hirarki. Otoritas adalah hal baik dan niscaya bagi
mereka. Karena ia selalu mengandaikan bahwa murid tidak tahu apa-apa, dan
bahkan berpotensi salah dan tersesat sebagai hal niscaya, karena itu guru harus
meluruskan secara moral. Dan secara pengetahuan, guru adalah subjek pentrasnfer
ilmu, sedangkan murid adalah wadah sebagai objek yang menampungnya. Kondisi-kondisi
itu dianggap sebagai realitas alami dan karena itu juga sebagai realitas ideal.
Dalam hal
moral, paradigma ini sangat merawat hubungan moralitas itu dalam hubungan
paternalistik, suatu hubungan kebapakan (maskulin) yang sangat menekankan
kepatuhan sang murid. Karena itu kritik dari murid bisa dianggap sebagai
pelanggaran berat dalam konteks ini.
Paradima konservatif
selalu menekankan harmoni dan menolak segala bentuk perbedaan-perbedaan
pendapat, dengan mengaggap hal-hal yang sifatnya konflik (pertentangan) sebagai
ancaman atas harmoni. Dalam konteks hubungan guru-murid maka yang harus ada
hanyalah kepatuhan semata. Begitupun dalam konteks pengelolaan sekolah, relasi
guru dengan sekolah haruslah harmonis dalam konteks budaya bisu. Guru haruslah
tentram, damai, dan tidak boleh mempunyai pendapat yang berbeda dengan sekolah.
Tidak ada otonomi guru, sebagai simbol pendistribusian kekuasaan sekolah, kalaupun
ada maka itu harus selaras dengan kebijakan sekolah. Pastinya perbedaan-perbedaan
pendapat dianggap tidak ideal. Karena itu sekolah hampir semuanya dijalankan
dengan penuh kalkulasi doktrin untuk konteks ini.
Pardigma konservatif,
selalu terjebak pada blaming victims,
yakni bentuk-bentuk pelimpahan kesalahan kepada objek sebagai pangkal dari persoalan
pendidikan yang ada. Objek yang dimaksud adalah pihak-pihak yang ditakdirkan
dalam posisi lemah. Dalam konteks hubungan guru-murid, maka murid adalah objek
yang dianggap selalu sebagai sumber persoalan itu sendiri. Misalnya banyak
murid tidak lulus, maka yang bermasalah adalah murid itu sendiri, dengan
penghakiman-penghakiman seperti: malas, bodoh, nakal, dsbnya.
Dalam konteks
hubungan sekolah dan guru, guru adalah objek yang dianggap sumber persoalan itu
sendiri. Dalam konteks hubungan pemerintah dan sekolah, maka sekolah sebagai
subjek yang lemah: karena itu dianggap sebagai sumber persoalan. Intinya akar
persoalan pendidikan apapun, dalam paradigma ini akan mengarah pada
relasi-relasi subjek yang lemah yang jadi pesakitan. Dan yang paling lemah atas keseluruhan subjek yang ada
dalam interaksi pendidikan itu adalah sang murid. Karena itu murid akan terus
berada sebagai subjek dan objek yang dipersoalkan dan dipermasalahkan. Oleh karena
itu, aturan dan sistem yang dibuat dari
paradigma ini, akan terus berakar pada upaya untuk menjadikan objek tadi
sebagai objek dari aturan itu sendiri. Murid diatur ini, itu, harus begini,
begitu dsbx.
Paradigma liberalisme
Bisa dikatakan,
di Indonesia, paradigma inilah (liberalis) sebagai ide-ide yang paling ‘popular’
dalam percaturan wacana-wacana pendidikan alternatif. Sudah banyak yang
berusaha mengembangkan ide-ide diluar dari paradigma konservatif di atas,
dengan menggunakan counter paradigma
liberalisme sebagai sumber ide dan gagasan.
Banyak fasilitator
menggunakan paradigma ini. Pengalaman penulis juga sewaktu terlibat di salah satu
LSM yang bergerak di bidang pendidikan, memperlihatkan bahwa pengaruh paradigma
ini sangat popular, dipakai sebagai alat analisis, sekaligus sebagai wacana
atas metode pendidikan alternatif. Paradigma ini bisa dikatakan antitesa dari
paradigma konservatif sebelumnya, karena itu ide-ide yang mendasari, sekaligus
yang menjadi isu pendidikan dari paradigma ini adalah berangkat secara otokritik
terhadap paradgima konservatif sebelumnya.
Filosofi dasar
dari aliran pemikiran liberalisme ini adalah upaya untuk menempatkan realitas
manusia sebagai subjek yang individual (kesadaran individu). Pemahaman ini cukup
memiliki kesadaran dalam mengidentifikasi bahwa, ada realitas yang tidak ideal
berjalan dalam pendidikan yang ada saat ini. Namun ia menempatkan, sekaligus
memahami bahwa persoalan pendidikan yang ada terletak pada manusianya, dalam
hal ini sumber daya manusia itu sendiri. Sekilas tampak bahwa gagasan ini, selangkah
lebih maju dari paradigma konservatif. Setidaknya paradigma ini sudah berlepas
diri dari perangkat akar dari paradigma konservatif, yang selama ini selalu
menempatkan murid sebagai sumber persoalan. Paradigma liberalis dalam konteks
ini menempatkan guru (Sumber Daya Manusia) sebagai akar pokok persoalannya.
Karena itu,
ide-ide solutif yang lahir dari paradigma ini adalah lebih menekankan pada
hal-hal yang bersifat metodologis. Karena ia menempatkan akar persoalan
pendidikan pada SDM, maka solusinya bagi mereka adalah memperbanyak pelatihan-pelatihan
bagi guru. Paradigma ini juga yang menguasai pikiran para pengambil kebijakan
hari ini, karena itu tidak heran ketika kebijakan pendidikan lebih banyak
bermuara ke hal-hal birokratis yang dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan
kualitas SDM guru, seperti: sertifikasi, dan segudang pelatihan yang ada.
Bagi mereka,
kualitas guru adalah sumber persoalannya. Analisa yang dipakai adalah kesadaran.
Ia mengasumsikan kesadaran guru masih rendah dalam memahami realitas tuntutan
pengajaran kekinian. Karena itu dalam pelatihan, model simulasi dipakai sebagai
alternatif metode. Apa produk gagasan yang dilahirkan dari paradigma ini? Mungkin
kita tidak asing lagi mendengar istilah-itilah: metode Cara Belajar Siswa Aktif
(CBSA), metode learning to doing, group dynamic class, dll. Persoalan pendidikan
tereduksi sebagai persoalan teknis dan metodologi semata dianggap sebagai solusi.
Dalam paradigma
ini, tampak ada upaya untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat struktural. Ia mengasumsikan
bahwa kesadaran itu lahir di ruang hampa. Persoalan guru tidak kreatif
misalnya, dianggap karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan, karena itu bagi
mereka, guru harus disadarkan akan hal itu dan diberi pelatihan. Dalam konteks
ini, guru adalah subjek otonom itu sendiri. Ia adalah sumber, sekaligus harapan
atas perbaikan persoalan-persoalan pendidikan yang ada.
Nampak,
bahwa paradigma liberalis juga terjebak pada blaming victims, hanya saja bedanya dengan paradigma konservatif
tadi, paradigma liberalis menempatkan guru secara otonom sebagai sumber
persoalan. Asumsi yang dibangun dari paradigma ini adalah: tidak ada persoalan
pada struktur, struktur yang ada sudah baik, tinggal menjalankannya, dan yang perlu diperbaiki adalah kualitas individu
itu sendiri (SDM), yang terdiri dari persoalan skill, mental, sikap dan
pengetahuan. Begitupun dalam memandang murid, paradigma ini akan selalu fokus
dan berorientasi pemberian dan perbaikan pada skill, mental, pengetahuan dan
sikap pada murid.
Pemahaman liberal
ini, sebenarnya merupakan pemahaman yang lahir dari tuntutan abad rasionalisme
di Eropa saat itu. Ia juga menjadi nafas bagi bangkitnya paham kapitalisme
global yang ada saat ini. Yang mengasumsikan persoalan kehidupan manusia
sebagai persoalan kualitas SDM semata. Karena itu pengaruhnya dalam pendidikan,
itu nampak pada segenap orientasi pendidikan yang ada saat ini, disetting untuk
bisa menjawab tuntutan-tuntutan pasar industri. Karena itu tidak mengherankan
ketika mereka yang menggunakan analisis ini dalam memandang pendidikan akan
selalu melihat bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan anak didik yang siap
bersaing dalam dunia industri. Pendidikan dijadikan pabrik untuk melahirkan
lulusan yang siap diakomodasi dalam pasar. Karena itu pendidikan harus berorientasi
kualitas skill yang nantinya dipakai untuk masuk dalam dunia kerja.
Pendidikan adalah
penyalur tenaga kerja untuk konteks ini. Nilai- nilai berupa skill, mental,
pengetahuan, dan sikap, adalah nilai-nilai yang didefinisikan dari sudut
pandang kapitalisme (pasar). Mental harus mental pasar, dan sikap pun harus
distandardisasi seperti dengan nilai sikap yang berlaku pada industri (perusahaan).
Untuk konteks yang lebih luas, pengelolaan pendidikan juga biasanya disetting,
menyerap nilai korporasi, dilihat dari aturan, kebiasaan dan nilai norma yang
ada.
Pengaruh paham
ini, cukup bahkan untuk mengubah orientasi pendidikan dari konteks ideologi
menuju konteks pasar---untuk hal ini,
saya akan menuliskan tulisan khusus untuk menjabarkan lebih jauh. Indikator-indikator
keberhasilan sekolah adalah sejauh mana produknya diserap dalam pasar. Ide-ide
tentang kompetisi, skill teknik, menjadi prioritas dalam konteks ini. Karena itu,
kualits guru yang dianggap tidak mumpuni adalah guru yang dianggap tidak
memiliki sikll teknik dari sudut pandang kebutuhan-kebutuhan pasar. Arah dari
keseluruhan proses yang ada dalam sekolah bermuara pada kebutuhan-kebutuhan
pasar. Karena itu skill SDM lah pokok persoalan pendidikan!
Paradigma kritisisme
Bisa dikata
bahwa pradigma kritis ini merupakan kritik terhadap paradigma konservatif dan
paradigma liberalis. Sering disebut, aliran paradigma kritis dalam madzhab
pengetahuan ini bermula pada sekelompok pemikir-pemikir sosial radikal di Jerman
saat itu yang dikenal sebagai Mazhab Frankfurt. Titik tolak keberadaan
paradigma ini adalah kritik itu sendiri yang berpangkal pada hal-hal yang
bersifat struktural. Dalam konteks isu pendidikan, paradigma ini bisa dikata
ikut membentuk aliran pemikiran dalam pendidikan yang khas yang sering dikenal
dengan istilah pedagogi kritis.
Apa yang
menjadi inti pokok pendarasan persoalan-persoalan pendidikan dari paradigma
kritis ini, adalah dengan melibatkan pembacaan struktural yang ada. Pendidikan sebagai
produk kebudayaan tidak lahir di ruang yang hampa, melainkan terkondisikan oleh
berbagai bias struktural yang ada.
Menggunakan pembacaan
struktural dalam melihat persoalan pendidikan, mengasumsikan bahwa kesadaran
itu sebagai bagian dari keberadaan struktur yang bersifat deterministik. Seperti
halnya kalau kita membaca persoalan kekerasan guru yang ada, paradigma
konservatis mungkin akan memandang itu sebagai bukan persoalan, kalaupun ia
adalah persoalan maka yang menjadi objek dipersalahkan adalah murid, sedangkan
paradigma liberalis kemungkinan akan menggiring hal itu ke guru. Kedua-duanya
sama dalam konteks mereduksi persoalan itu (kekerasan guru itu) dalam ranah
moralitas dan personal. Dua paradigma itu bersepaham untuk tidak mengaitkan hal
itu dengan struktur yang ada. Sebagai sebuah persoalan moral dan personal maka
hal itu disebut sebagai persoalan kasuistik dan insendentil.
Sedangkan pendekatan
kritis berusaha untuk membaca hal itu sebagai persoalan yang tak terpisah dari persoalan struktural
yang ada. Kekerasan guru terhadap murid, adalah bagian dari konstruksi
struktural atas relasi hubungan guru-murid yang timpang, penuh otoritas. Setali
dengan timpangnya hubungan kuasa antara sekolah dengan negara. Standardisasi yang
juga adalah pemaksaan dari negara, akan selalu menciptakan celah pemaksaan dalam
konteks hubungan otoritatif antara sekolah terhadap guru, dan hingga antara
guru terhadap murid. Ini seperti sebuah spiral struktural. Karena itu,
pendektan struktural akan selalu mendorong perbaikan di tingkat struktural.
Banyak hal
dimana pendekatan struktural ini dapat dipakai untuk melakukan pembacaan atas
realitas persoalan pendidikan yang mencuat. Paradigma kritis akan menghendaki perubahan struktur secara fundamental, menghindari
hal-hal yang bersifat reformis seperti penggunaan standar ganda dari sebuah
nilai. Standar ganda yang dimaksud cukup luas, seperti halnya: menerima prinsip
demokrasi dalam sekolah tidaklah tepat ketika itu hanya dilihat secara
aksiologi dari hubungannya antara guru dan murid, tetapi juga harus dilihat
dari hubungan antara guru dengan guru, guru dan sekolah, bahkan hingga dari
hubungan pemerintah dan sekolah. Karena struktur itu semua saling terkait
secara nilai.
Paradigma kritis menghendaki bahwa orientasi
dari pendidikan haruslah mengarah pada sebuah proses pembebasan. Pembebasan dari
segala bentuk penindasan baik kulutral maupun struktural. Ia menempatkan persoalan pendidikan yang ada
berangkat dari sistem pendidikan yang tidak manusiawi, mendegradasi hal-hal
manusiawi terhadap pendidik dan murid, karena itu paradigma kritis mendorong
perubahan kepada prinsip emansipatoris, humanis dan demokratis di segala bidang
pendidikan.
Asumsi yang dibangun dari pendekatan ini adalah,
bahwa, persoalan pendidikan sama dengan persoalan moral, merupakan perkara yang
tidak lahir di ruang yang hampa begitu saja, ia merupakan bagian dialektis dari
perkara-perkara struktural. Kalau misalnya ada pelajar yang selalu dianggap
melanggar aturan sekolah, bukan berarti bahwa ia senang melanggar, mungkin saja
ia adalah reaksi dari produk aturan yang terus hanya menjdikan sebagai objek aturan,
bukan sebagai subjek aturan itu sendiri. Subjek aturan itu sendiri yang
dimaksud disini, mengasumsikan adanya proses penglibatan murid dalam menentukan
apa yang baik dan tidak baik yang muncul lewat kesepatakan-kesepakatan
demokratis. Jadi ini adalah persoalan struktural, tidak melulu melihatnya
sebagai persoalan personal, moralis, sikap dll seperti yang diajarkan oleh
paradigma liberalis, apalagi konservatis.
Saya rasa, banyak hal yang harus
direinterpretasi ulang atas tatanan lama yang berjalan hari ini. Tugas terberat
sebenarnya bukan pada bagaimana memberi solusi atas persoalan-persoalan
pendidikan yang mencuat, tetapi bagaimana memahami persoalan itu sendiri. (berlanjut)
Tabik..
Penulis
Muhammad Ruslan