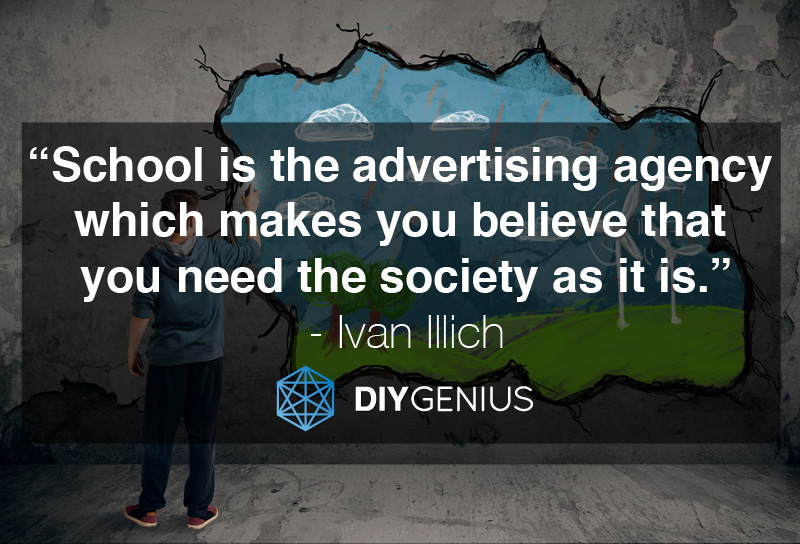|
| sumber gambar: www.majalahkartini.co.id |
Kasus pemukulan guru terhadap siswa yang berujung pada
ancaman pidana, yang marak belakangan
ini terjadi, memunculkan kembali wajah ironi pendidikan
yang berjalan saat ini. Kasus Nurmayani Salam, seorang guru SMP di Bantaeng Sul-Sel
yang kini mendekam dalam bui (12/5). Hanya berselang hari setelah itu kasus
yang sama kembali ter-publish, kejadian
menimpa Muh Arsal, guru asal Bantaeng, juga tersandung kasus yang sama:
pemukulan, yang berujung gugatan penyeleseian lewat hukum.
Membaca hal itu, setidaknya ada dua pokok persoalan dasar
yang terjadi. Yang pertama adalah kasus pemukulan atau kekerasan terhadap
siswa. Kasus ini bisa dianggap sebagai hal yang bukan kali ini saja terjadi, ia
memiliki pertautan pola dengan banyaknya kasus-kasus yang pernah terjadi, hanya
saja masyarakat melihatnya dari sudut pandang yang berbeda saat itu dengan
ketika hal itu terjadi saat ini. Persoalan kedua adalah persoalan pidana. Kekerasan
yang dipidanankan. Pendisiplinan dengan tangan oleh guru terhadap siswa saat ini, sudah bisa
terkategorikan sebagai praktik kekerasan. Hal ini tidak lepas dari perubahan
cara pandang masyarakat dan tentunya negara lewat perangkat aturan yang mengatur
hal ini, sebagai bagian dari dinamika politik pendidikan yang berjalan.
Membaca persoalan ini (kekerasan guru terhadap siswa yang
berujung pidana), belum utuh ketika hanya sampai pembacaan lewat pendekatan
personal apalagi pendekatan moral, tetapi harus melampaui hal itu, yakni masuk
lewat pembacaan struktural atasnya. Tulisan ini mencoba menelisik lewat hal
itu.
Produk kesadaran
orde yang berbeda
Munculnya riak kekerasan yang berujung pada jalur hukum
ini, bukan kali ini saja terjadi. Mungkin di masa-masa yang lalu, praktik yang
sama lebih intens terjadi, akan tetapi upaya untuk “memperkasuskan” hal itu lewat
jalur hukum, menjadi fenomena lain tersendiri saat ini di tengah alam demokrasi
yang mengharuskan kesetaraan sebagai warisan nilai orde reformasi.
Ini menjadi bentuk
nyata terjadinya kontradiksi yang ada, berujung pada gesekan dari sebuah realitas
pemahaman yang berbeda dengan realitas tuntutan kekinian. Guru yang merupakan produk tatanan lama, dengan realitas
pendidikan dan siswa yang hidup dalam tatanan budaya baru. Guru dengan kesadaran
pedagogi orde baru yang serba militeristik, berbenturan dengan tuntutan
kesadaran demokrasi dan egaliter ditubuh pendidikan yang menjadi warisan orde
reformasi.
Memang tak mudah, seorang guru yang dibentuk dan
dihasilkan oleh zaman orde baru untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan metode
pendidikan yang dituntut di alam reformasi saat ini. Perubahan orde tersebut,
juga ikut merubah tatanan hubungan guru-murid. Otoritas guru terhadap murid
sedikit demi sedikit ditanggalkan. Ini seperti, sulitnya para militer yang pernah
hidup di alam politik orde baru dengan segenap otoritasnya, untuk bisa
menyesuaikan perannya di era reformasi yang menjunjung tinggi kekuatan sipil
saat ini. Itu terbukti dari kisruh politik yang terjadi belakangan ini (isu
kebangkitan PKI), yang melibatkan TNI akhir-akhir ini.
Saya sering kali bertemu guru-guru yang dididik di era
orde baru, mengajar sampai saat ini. Dan saat saya ajak untuk berdiskusi dengan
kondisi pendidikan saat ini, hampir semua berakhir dalam romantika masa lalu, suatu
romantika otoritas atas tatanan pedagogi yang militeristik ala orde baru yang
dianggap ideal. Gagasan pendidsiplinan yang paling dikedepankan itu, tidak
lepas dan tidak pernah alpha dari definisi-definisi “kekerasaan” dari sudut
pandang kekinian.
Karena itu, sangat nampak , para guru yang tejerat kasus
yang sama dengan Guru Nurmayani, hampir didominasi oleh guru-guru yang secara
pedagogi terbentuk di era orde baru, dijerat dengan aturan yang disemai di orde
reformasi. Memang cukup mengundang empati sekaligus dilema.
Empati dan dilema
Empati, saat seorang guru “dipenjarakan” oleh siswanya
sendiri. Kita, dengan masyarakat kita, yang masih kental dengan budaya
paternalisme-nya, akan memandang hal itu sebagai ironi kalau bukan bentuk
“kedurhakaan” siswa terhadap guru. Tetapi, di satu sisi perjalanan demokrasi
dan emasipasi sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi, termasuk di dunia
pendidikan, seolah menafikan hal itu. Sebagai kaum terpelajar tentu kita akan
melihat dan mengakui pula bahwa ada hak-hak siswa sekalipun yang harus dihormati.
Konsep egalitarianisme ini, adalah pendobrakan atas tatanan feodalisme dalam
pendidikan, dengan menempatkan anak pada tempat yang layak dan manusiawi, yang
mana hak-haknya harus dijaga, termasuk keberadaan hukum yang harus melindunginya
dari praktik kekerasan guru atas nama otoritas.
Dilema ini muncul sebenarnya merepresentasikan antara
tuntutan nilai-nilai baru yang ingin dijunjung tinggi dalam pendidikan, bertautan
dalam persinggungan dengan lambangnya penerimaan masyarakat atas nilai
tersebut. Ini seperti demokrasi di segala bidang yang turun dari atas, masih
terbentur dengan pemahaman dan penerimaan di tingkat masyarakat, yang masih
berada dalam zona pikir yang lama (feodal). Termasuk di bidang pendidikan.
Kasus Nurmayani ini menggambarkan hal itu, masyarakat
lebih banyak menyebut dan menimpakan kasus “dipenjarakannya guru” sebagai
hal-hal yang keterlaluan bahkan dianggap tidak manusiawi. Meskipun dari sudut
pandang “kesetaraan guru-murid” kekerasan guru juga adalah bentuk hal-hal tidak
manusiawi terhadap siswa, karena itu kekerasan tidak bisa berpaling jauh dari
pidana. Lagi-lagi, perbedaan pandang ini, mirip perdebatan-perdebatan kaum
tradisionalis versus kaum modernis dalam memandang persoalan.
Politik pendidikan
dalam hubungan guru dan siswa
Dalam upaya mengurai keterhubungan normatif antara guru
dan siswa, kita tidak bisa melepaskan dari politik pendidikan yang berjalan
lewat kebijakan-kebijakan pendidikan dalam rentang history yang berbeda. Kalau
kita bandingkan hubungan guru-siswa di zaman Belanda (khsususnya
sekolah-sekolah Eropa Belanda) saat itu, akan nampak hubungan guru-siswa
merepresentasikan budaya Eropa yang penuh egaliter antara tuan guru dan tuan
siswa. Terlepas dari politik diskriminatif yang terjadi dalam mengakses
pendidikan saat itu.
Sedangkan pengelolaan pendidikan oleh pribumi, banyak tidaknya
tidak bisa lepas dari tatanan budaya yang masih berkarakter hirarki. Hubungan
guru-siswa terpola dalam garis otoritas, khususnya otoritas karena faktor
budaya. Di surau-surau misalnya hubungan kiai-santri merepresentasikan hal itu.
Karakter hubungan hierarkisasi tersebut semakin menguat
lewat pertautannya dengan budaya paternalisme masyarakat yang dikuatkan sejak
orde baru. Orde baru berhasil mengkonstruksi hubungan guru-siswa dalam hubungan
otoritas penjinakan yang paling intim dalam ikatan “orang tua-anak atau
bapak-anak” dalam pendidikan.
Konstruksi ikatan “hubungan bapak-anak” yang melekat
dalam pendidikan saat ini, tidak lepas dari atmosfir politik orde baru yang
dihembuskan Soeharto saat itu. Suatu tatanan politik yang penuh dengan
kebiajakan-kebijakan penjinakkan, hingga pembungkaman, tak terkecuali kebijakan
politik itu masuk di ranah ruang kesadaran paling intim bernama pendidikan yang
menciptakan hubungan guru-siswa sebagai representasi hubungan bapak-anak.
Seperti lazimnya bapak terhadap anak, anak menjadi objek yang
dikuasai, dimana bapak dengan otoritas yang penuh, sedangkan anak
direpresentasikan sebagai keberadaan yang harus patuh dan taat. Seperti halnya Soeharto
yang merepresentasikan diri sebagai “bapak” pembangunan, dan memposisikan rakyat
sebagai “anak” yang harus mengikut, tidak boleh membantah apalagi melawan sang
bapak. Sebuah kebijakan politik penjinakkan atas nama stabilisasi, yang
berujung pembungkaman hingga kekerasan (represif). Dan secara politik
pendidikan, model-model ini disemai lewat tradisi pedagogi yang bertendensi
maskulin, penuh dengan otoritas, penguasaan, dan pendisiplinan yang berbaur
dengan budaya paternalisme (kebapakan), yang secara tidak langsung memberi
pendasaran-pendasaran kultural terjadinya “legalisasi” praktik “kekerasan”
dalam pendidikan.
Namun saat orde reformasi, dimana isu-isu tentang
kesetaraan dan HAM sudah merembes, mempengaruhi segala bidang, tak terkecuali
dalam pendidikan itu sendiri. Konstruksi kebapakan dalam relasi guru-siswa juga
sepertinya mengalami perubahan penafsiran yang signifikan, seiring dengan
disemainya ide-ide tentang kesetaran dan HAM itu sendiri. Guru dengan
otoritasnya (khususnya dalam memberi sanksi) sedikit demi sedikit dilucuti.
Berkaca pada kasus Nurmayani, cubitan sebagai upaya pendisiplinan, justru bisa
berujung pada persoalan pidana, terkategorikan sebagai praktik kekerasan. Hal
ini tiada lain merupakan upaya untuk menerjemahkan hubungan kesetaraan guru-murid
itu sendiri.
Hubungan kesetaraan guru-murid, bukan hanya ada dalam
ruang lingkup pemberian sanksi yang sangat dibatasi bentuknya, tapi juga memang
sudah menjalar ke berbagai aspek sistem pendidikan itu sendiri. Seperti metode
pembelajaran, dll. Tuntutan-tuntutan perubahan metode pembelajaran di sekolah
sudah sangat menjauh dari praktik pembelajaran orde baru yang terus
memposisikan siswa sebagai anak yang harus dikontrol dan dikuasai, atau dilucuti
perangai kekuasaan siswa. Tuntutan itu mengarah, lagi-lagi pada lahirnya konsep
pembelajaran yang memposisikan siswa dalam pola kesetaraan. Kesetaraan hubungan
guru-siswa yang terpola dalam hubungan
subjek-subjek, bukan lagi subjek-objek.
Kegagalan memahami hingga kegagalan menerjemahkan konsep-konsep
perubahan mendasar politik pendidikan ini bagi guru, bisa saja berujung sama
dengan kasus-kasus Nurmayani untuk yang lain. Mendorong kembali lahirnya
gesekan-gesekan yang hanya akan memperpanjang kasus kekerasan yang berujung
pemidanaan guru oleh siswanya sendiri. Apalagi di saat sekolah dan kondisi
pendidikan hari ini yang semakin kering secara ideologi, suatu ironi saat hubungan
sekolah, guru, dan siswa semakin kehilangan dimensi hubungan ideologisnya.
Hubungan ini semakin pragmatis, berkarakter transaksional. Ini tidak lepas
sebagai sisi lain dari perjalanan arah pendidikan yang semakin mendekatkan diri
pada pasar, yang justru menjauh dari hal-hal yang bersifat ideologis saat ini. Ikatan
guru-siswa menjadi longgar, empati makin hilang, “tanpa rasa bersalah dari
lubuk nurani” seorang guru bisa dengan mudahnya melakukan praktik kekerasan
terhdap muridnya sendiri, di saat yang sama seorang anak yang juga “tanpa rasa
bersalah dari lubuk nurani” dengan mudahnya menuntut gurunya sendiri lewat
pidana.
Muhammad Ruslan
repost untuk tujuan pendidikan, sumber: http://www.kompasiana.com/2220/pembacaan-struktural-atas-kasus-kekerasan-guru-berkaca-pada-kasus-nurmayani_574346baad9273e9078b4580