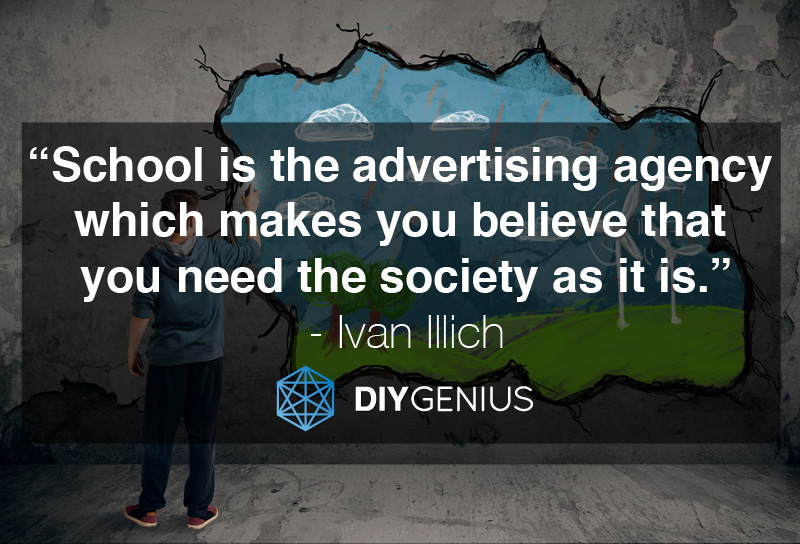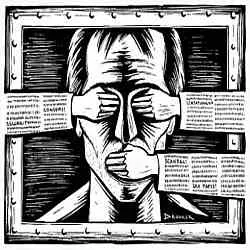Tetapi pertanyaanku,
Membenturi meja-meja kekuasaan yang macet
Dan papan tulis - papan tulis para pendidik yang terlepas dari
persoalan kehidupan
Sajakku, pamflet masa darurat
Apalah artinya renda-renda kesenian
Bila terpisah dari derita lingkungan
Apalah artinya berfikir
Bila terpisah dari masalah kehidupan
Kepadamu, aku bertanya..(?)
(WS. Rendra: 1977)
---------
Berbicara pembelajaran kontekstual, dapat dipahami sebagai suatu konsep yang
lahir, sebagai anti-tesa, kritik atas model pembelajaran tekstual. Dalam konteks
ini, penulis menyederhanakan perihal konsep pembelajaran ini, dalam dua
kerangka konsep yang berbeda, yakni pembelajaran tekstual dan pembelajaran
kontekstual.
Perbedaan dasarnya
Saat ini, metode yang mendominasi pengajaran-pengajaran
konvensional umumnya masih berkutat pada metode pembelajaran tekstual. Pembelajaran
tekstual ini, berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah
teks, dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks
(buku-buku) sebagai sumber primer referensi, dan bahkan sebagai satu-satunya
alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang statis, kebenarannya bertumpu pada teks.
Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya
titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan
sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas
terberikan (oleh teks). Pembelajaran
tekstual memposisikan proses belajar-mengajar sebagai proses transformasi
distribusi teks, dari teks kepada siswa lewat perantara guru.
Berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual, metode ini
melibatkan pengalaman praktis sebagai sarana memahami dan menemukan ilmu. Teks
hanya referensi, yang harus didialogkan
dengan pengalaman praktis. Pengalaman praktis dapat berupa pengalaman yang
dialami secara langsung hingga dengan melibatkan realitas persoalan praktis
yang nyata terjadi.
Metode pembelajaran kontekstual, melibatkan penalaran siswa terhadap
realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan
dan menganalisis. Oleh karena itu,
metode ini mensyaratkan wacana yang dibedah adalah representasi dari
persoalan-persoalan hidup sehari-hari, yang dialami secara bersama. Ilmu diproduksi
bukan sesuatu yang terberi (given),
dan memutlakkan pembuktian secara empirik, bertitik tolak pada realitas
kehidupan itu sendiri. Secara metodologi, aksiologi, ontolgi, dan epistemologi,
semuanya bersandar pada konteks kehidupan itu sendiri, tidak terpisah atau tidak
memisahkan diri dari persoalan kehidupan.
Perspektif sejarah
Dalam konteks sejarah, Pembelajaran kontekstual maupun tekstual
ini, tergolong sulit untuk dilacak dengan pasti keberadaannya -- yang mana yang mendahului yang mana. Namun,
karakter dua konsep tersebut, sangat mudah dipisah dan dipahami perbedaannya,
kalau saja ia ditarik keluar dari perdebatan sejarah, masuk dalam ranah kajian
filosofis.
Kalaupun ingin disinggung pokok-pokok sejarahnya, alat analisis
yang mudah dipakai pun tetap dengan menggunakan pendekatan filsafat, yakni
filsafat sejarah. Yakni melihat kecenderungan pola, karakter suatu konsep, dan
menemukan relevansinya dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat lampau, untuk
mengidentifikasi suatu kondisi-kondisi sejarah yang objektif yang mengkondisikannya.
Kalau saja, perbedaan pembelajaran tekstual dan kontekstual,
disederhanakan dalam ranah keberadaan teks, yang menjadi kriteria utama pembelajaran
tekstual, maka kita menyimpulkan bahwa model pembelajaran kontesktuallah
pertama dikenal, dengan memantik suatu asumsi bahwa, manusia, pertama kali belajar
dan memahami realitas, langsung dengan konteks kehidupan, bergelut tanpa
perntara teks[1]. Akan
tetapi kalau ditinjau dari kriteria normativitas otoritas, yang menjadi karakter
pembelajaran tekstual, maka kesimpulannya pun bisa berbanding terbalik dari kesimpulan
sebelumnya. Kemungkinan ketiga adalah dua-duanya dipakai, tercampur antar satu
sama lain, tanpa ada ruang untuk melihatnya sebagai dua konsep yang cenderung
dipertentangkan sebagai suatu konsep pada zaman sebelumnya, tidak seperti
sekarang ini.
Meninjau dari
sudut pandang kekinian
Metode pembelajaran tekstual, cenderung dominan saat ini, disebabkan
banyak faktor, salah satunya adalah faktor sejarah dan faktor sosial. Karakter dari
masyarakat yang masih sulit bertransformasi meninggalkan pola kehidupan feodalisme,
atau lebih tepatnya sisa-sisa feodalisme masa lalu, yang masih bercokol dibenak
masyarakat, yang membuat metode pembelajaran tekstual ini menemukan ladangnya. Jadi
ada pertautan sejarah yang khas, antara
model pembelajaran tekstual dengan sistem sosial masyrakat.
Selain itu, karakter “keber-agama-an” yang gamang, kaku, rigid,
penuh otoritas dan sangat skriptualis, yang hampir menjadi ciri kebergamaan
masyarakat dari dulu sampai sekarang, ikut mengkondisikan metode pembelajaran
tekstual ini diterima dan bertahan. Masyarakat yang hidup bertahun-tahun,
bahkan berabad-abad, dalam tradisi bergama seperti ini, kesulitan untuk
memisahkan pola pembelajaran agama dan ilmu.
Namun, yang paling
menghambat pembelajaran kontekstual ini, dan semakin membuat model pembelajaran
tekstual ini bertahan, tidak lepas dari peran kekuasaan yang membungkam, lewat
segenap aturan persekolahan dan kurikulum. Model top to bottom, yang menjadi tipikal karakter pembelajaran tekstual, juga selaras, dan merupakan
alat kekuasaan itu sendiri, yang nyata hadir untuk menjinakkan dan mengontrol
kesadaran, bukan menyadarkan. Itu sepertinya sudah menjadi karakter kekuasaan,
dimanapun.
Berbeda dengan pembelajaran kontekstual yang menuntut adanya
proses penyadaran, refleksi kritis yang harus berangkat dari persoalan nyata (bottom to up). Karena itu sangat sulit
untuk memahami model pembelajaran kontekstual ini disemai dan diharapkan tumbuh
dari bilik-bilik temboh kokoh sistem persekolahan formal yang dibangun oleh
kekuasaan sekarang ini. Terdapat kontradiksi, antara struktur yang ada.
Meyakini dan mengharapkan model
pembelajaran kontekstual, mensyaratkan adanya alternatif sistem “persekolahan”
di luar kaidah formal yang ada. Itu berarti, hanya ada satu kalimat, BANGUN
PEDAGOGI ALTERNATIF!
Penulis
Muhammad Ruslan
[1] Pembelajaran
yang dimaksud disini, tidak diterjemahkan dalam konteks persekolahan formal
semata.