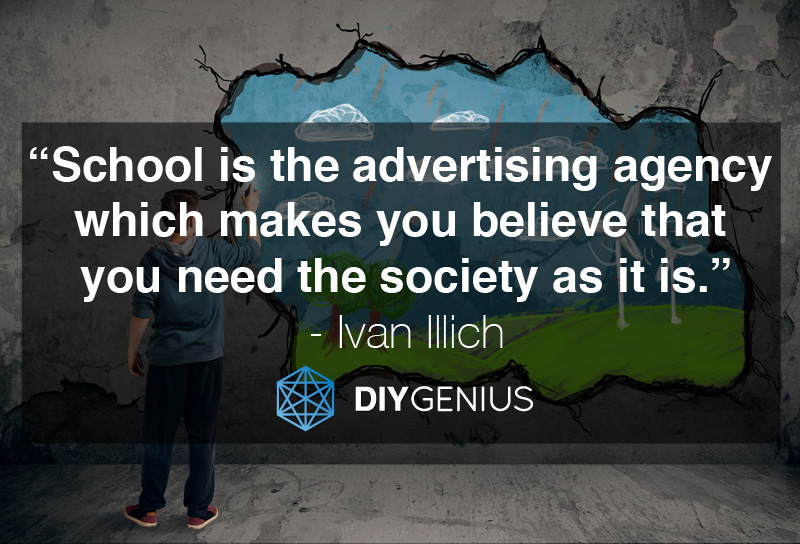"Saat seseorang mengambil alih ladang tempat seseorang lain
membuatmu terusir, siapapun itu kalian harus menghindar darinya saat bertemu di
jalan! Kalian harus menghindar darinya di jalan-jalan kota! kalian harus
menghindar darinya di toko! Kalian harus menghidar darinya di ladang dan di
tempat umum! Dan bahkan di tempat ibadah sekalipun dengan membiarkannya
sendiri, memberinya pengucilan, mengasingkannya dari tempat ini! Kalian harus
menunjukkan padanya sikap benci terhadap tindak kejahatan yang dia lakukan
terhadapmu."
Salah satu penggalan dari narasi pidato Stewart Parnel, yang
menyerukan aksi pemboikotan, yang akhirnya dikenal dengan istilah aksi
"boikot".
Parnel adalah pemimpin Liga Lahan Irlandia, yang memimpin
pemboikotan-perlawanan terhadap kebijakan tuan tanah Lord Erne lewat kaki
tangannya yang bernama Kapten Boycott (Charles Boycott), 1880.
Istilah boikot ini awal mulanya adalah adaptasi sarkas dari nama
Kapten Boycott itu sendiri, yang sempat popular di media-media Inggris saat
itu.
Ketika tuan tanah Lord Erne lewat tangan kanannya Charles Boycott
menolak permintaan petani untuk menurunkan harga sewa lahan hingga 25%, hal itu
memantik marah para petani yang tercekik oleh sewa lahan yang tinggi ditambah
panen yang buruk. Sebagai reaksi para buruh tani mengorganisir diri untuk
secara bersama-sama melakukan boikot, lewat aksi pengucilan, penolakan untuk
bekerja, dan penolakan untuk bekerjasama dengan Kapten Boycott.
Hasilnya, ketiadaan orang yang ingin bekerja untuk Kapten Boycott
membuatnya kesulitan mengontrol dan memanen hasil panennya, hingga akhirnya
keputusan mendatangkan pekerja dari luar yang membuat ongkos produksinya
membengkak drastis membuatnya bangkrut.
Dari situ sejarah tentang pemboikotan dan kemenangan orang-orang
kecil inilah yang kemudian membuat aksi boikot menjalar ke banyak negara
berkembang sebagai alternatif perlawanan orang-orang kecil melawan elit-elit
kolonial yang berkuasa.
Tentang bagaimana kaum Republik pada masa perjuangan kemerdekaan
menemukan dan menggunakan boikot sebagai alat perlawanan, novel Pramoedya Jejak
Langkah cukup apik menuliskan hal itu. "Bukan golongan kuat saja punya kekuatan,
juga golongan lemah. Tuan, golongan lemah bisa menunjukkan kekuatan diri
sebenarnya. Boikot, Tuan, perwujudan kekuatan dari golongan lemah!".
Di tengah situasi sosial politik kolonial yang menjarah banyak
negara-negara kecil tak terkecuali Indonesia pada masa kolonial Belanda, boikot
muncul sebagai senjata yang dianggap berkemajuan pada saat itu seturut dengan
"berorganisasi". Dengan boikot rakyat kecil seperti menemukan alat
yang tepat untuk menggebuk sekali pukul . Itu cukup untuk membuat Belanda pada
saat itu keteteran karena pabrik-pabrik perkebunan dan gula mereka benar-benar
kandas.
Ketika tangan-tangan pekerja berhenti, maka dengan sendirinya arus
perputaran akumulasi modal produksi juga berhenti. Boikot dan mogok, seperti
menjadi perwujudan praktis dari kata-kata Tan Malaka yang mengatakan: "Sesungguhnya
bukanlah kaum pekerja yang bergantung pada kaum modal, tapi kaum modallah yang
bergantung pada kaum pekerja". Dan itu terbukti bagaimana para
elit meradang ketika tangan kasar pekerja itu berhenti.
Pada titik ini, Boikot menjadi alat
politik kaum tertindas dalam sejarah perlawanan yang paling ampuh untuk memaksa
para elit kolonial untuk membuat keputusan politik penting. Arus modal yang
tergerus bahkan terhenti, tidak hanya sanggup menghentikan dan menghancurkan
akumulasi kapital, tapi juga bisa membuat tank-tank lapis baja berhenti,
pabrik-pabrik senjata menjadi redup.
#BoikotProduk yang mendukung
zionisme israel
#FreePalestine